Tak perlu bertele-tele: sepakbola Indonesia memang lebih suka yang serba instan, tak begitu peduli dengan pembinaan, melulu bicara prestasi seakan-akan prestasi tak ubahnya hujan yang bisa tercurah begitu saja dari atas langit sana. Lalu, apa jadinya jika kompetisi yunior atau kelompok umur yang sedianya dibangun untuk pembinaan pun ternyata lebih peduli dengan hasil dan prestasi?
Terbetik kabar kalau Rigan Agachi, pemain berdarah Indonesia yang sempat direkrut oleh PSV Eindhoven, terpaksa dibuang oleh PSV karena skandal pencurian umur. Jika benar, itu tentu tidak terlalu mengherankan. Anda hanya perlu memanfaatkan mesin pencari untuk menemukan kasus pencurian umur dalam kompetisi atau turnamen sepakbola kelompok yunior di Indonesia sampai sekarang masih saja direcoki oleh kasus pencurian umur. Ya, sampai sekarang.
Itu baru dari aspek yang paling kelihatan. Bagaimana dengan mental para pengelola SSB atau para orang tua pemain yunior? Sama saja, setidaknya seperti yang saya lihat dan saksikan sendiri pada hari Minggu kemarin di Lapangan AS-IOP, Senayan, dalam Liga Kompas-Gramedia U-14.
Sengaja saya datang bersama Hedi ke sana. Sudah lama saya tidak melihat anak-anak kecil bermain bola. Terlalu sukar sekarang untuk sekadar melihat anak-anak bermain bola. Saya sudah lupa kapan terakhir melihat anak-anak bermain bola di Jakarta, entah di tanah kosong, halaman rumah atau jalanan gang. Jika pulang kampung, saya mudah saja menemukan anak-anak kecil main bola. Ke luar dari rumah dan berdiri di beranda pada sore hari saja, mata saya dengan mudah melihat anak-anak kecil mengejar bola dengan kaki telanjang.
Dihajar oleh tayangan Piala Dunia sebulan lalu disusul tayangan babak 8 besar Piala Indonesia agak membuat mata saya suka njempalik, kadang kedip-kedip gak jelas, walau pun tetap saya tonton. Menonton pertandingan sepak bola anak-anak, saya kira, bisa terasa lebih menyenangkan. Saya bisa merasakan kegembiraan, juga sebentuk kemurnian suka-cita anak-anak dalam mengejar bola, hanya berlari dan mengejar bola dengan penuh kesenangan yang tanpa beban, mungkin juga tanpa pretensi selain karena mereka hanya dan hanya mencintai si kulit bundar.
Eduardo Galeano, sastrawan Uruguay yang menulis buku Football in Sun and Shadow, juga mengaku masih sering berhenti di tengah jalan saat melihat anak-anak bermain bola. Kurang lebih dengan alasan yang sama: untuk mereguk "kemurnian" sebuah permainan yang penuh kegembiraan dan suka cita.
Maka, pada siang yang panas, saya bersama Hedi bergerak dari Tanjung Barat menuju Senayan. Singgah sebentar di Senopati, kami berdua memapras jarak sekitar 2,5 km dari Senopati menuju lapangan AS-IOP, lokasi pertandingan, dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, sedang berlangsung pertandingan terakhir antara SSB Ricky Yakobi versus SSB Apac Inti. Kami langsung duduk di tribun yang hanya terdiri dua tingkat di sisi lapangan, tak jauh dari meja inspektur pertandingan.
Pertandingan baru saja dimulai. Kami cukup lega karena anak-anak ini sudah bermain dengan menggunakan pola empat bek sejajar, bukan lagi pola 2 stopper + 1 libero yang sudah kapiran tapi ajaibnya masih dipakai oleh tim nasional Indonesia. Beberapa dari mereka memiliki postur yang cukup ideal untuk anak-anak seumuran itu.
Tapi pemain gelandang bernomor punggung 8 dari SSB Ricky Yacobi mencuri perhatian. Ia pemain dengan postur paling kecil di lapangan, badannya juga kurus, bukan gempal. Tapi dia memiliki passing yang selalu akurat, kontrol bola yang bagus, dan penempatan posisi yang juga tepat. Di ujung babak pertama, dalam sebuah serangan balik yang cepat, dia tiba-tiba muncul di kotak penalti dan mengkonversi umpan dari sayap menjadi sebuah gol.
Kami menikmati pertandingan itu, sampai kemudian kenikmatan itu teranggu saat beberapa orang suporter dari SSB Ricky Yacobi beberapa dari mereka adalah orang tua pemain-- mulai berteriak-teriak. Mereka meneriaki dan memaki wasit dalam beberapa insiden. Puncaknya, saat penyerang lincah dengan mobilitas yang tinggi bernomor punggung 10 dari SSB Apac Inti menguasai bola di sisi kiri, salah satu dari mereka berteriak: "Patahin aja kakinya, patahin.
Terus terang saya geleng-geleng kepala. Hedi hanya diam saja. Saya tidak tahu apa motivasi dan maksud dari teriakan-teriakan intimidatif macam itu. Sebentuk teror untuk pemain lawan? Itu jelas. Puji Tuhan, pemain bernomor punggung 10 itu tak keder, dan masih tetap berani mengganggu pertahanan SSB Ricky Yacobi dari sisi kiri, titik datangnya teriakan-teriakan intimidatif dan meneror itu.
Bagusnya, saat jeda pertandingan, inspektur pertandingan memanggil para suporter itu ke meja pertandingan. Entah apa yang dikatakan oleh panitia pertandingan, tapi sejak itu mereka diam dan tak lagi berteriak-teriak sepanjang babak kedua.
Saya ingat, saat orang-orang itu melintas di depan kami, salah seorang penonton di depan saya berkata: "Kalau mau rusuh-rusuhan di Liga Super saja sono!"
Saya kira perkataan itu benar. Pertama, ini sepak bola anak-anak, turnamen yang sengaja dibuat untuk pembinaan pemain muda. Kendati ini sebuah turnamen yang berujung iming-iming hadiah dan prestasi, tujuan utamanya tetap pembinaan. Prestasi, dengan demikian, tidak boleh mengalahkan motivasi pembinaan itu. Itu sebabnya pencurian umur haram betul. Itu sebabnya jatah pergantian pemain pun tidak hanya 3 pemain seperti dalam kompetisi senior, sehingga setiap anak bisa mencicipi iklim kompetisi, tetap mendapatkan ruang untuk menjajal hasil latihannya dalam sebuah pertandingan resmi.
Meneriaki wasit jelas tidak elok. Itu hanya akan membuat anak-anak pemilik masa depan sepak bola Indonesia sudah dibiasakan dengan iklim yang tidak sehat, iklim penuh syak-wasangka dan itu perlahan bisa merusak. Padahal, penonton mana pun yang melihat dengan jernih mengetahui bahwa wasit sudah memimpin pertandingan dengan baik.
Dan menyemangati para pemain dengan berteriak "patahin aja kakinya" adalah kanker busuk yang mestinya tak boleh ada dalam kompetisi sepak bola yunior. Gile aje kalau sedari muda anak-anak ini sudah diajari main kayu dan asal tebas.
Menjadi juara dan pemenang sebuah turnamen yunior jelas prestasi membanggakan, tapi janganlah itu membikin kita permisif. Lagi pula, bukankah kebanggan sebuah SSB adalah saat bisa bilang: "Pemain timnas itu dulu belajar main bola dari SSB gue."
Kedua, penonton itu juga benar saat bilang: "Kalau mau rusuh-rusuhan di Liga Super saja sono!"
Itu ucapan spontan yang dengan amat baik menggambarkan alam (bawah) sadar penonton tersebut yang merasa bahwa puncak kompetisi sepak bola di Indonesia adalah juga puncak kebobrokan sepak bola Indonesia. "Lihat, Liga Super tidak dipandang sebagai puncak prestasi, tapi justru ajang untuk rusuh-rusuhan. Dan ini suara akar rumpur, tepatnya suara orang yang peduli dengan pembinaan pemain muda," kira-kira begitu komentar Hedi.
Bagi saya, ucapan spontan itu berarti: "Hei, dari sinilah benang kusut prestasi sepak bola Indonesia bisa mulai dipecahkan, itu pun jika mau!"
Fyuh, hari Minggu yang aneh.
*) Arsip lama, ditulis pada 26 Juli 2010







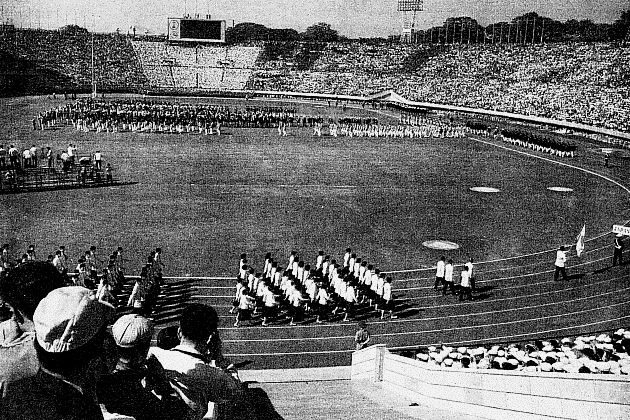

Komentar