Orang Uruguay punya istilah untuk menyebut seorang pelatih sepakbola yang hebat: maestro. Tentu ada beberapa kriteria bagi seorang pelatih jika ingin disebut sebagai maestro. Barangkali ukuran yang paling jelas dan terukur adalah ihwal seberapa banyak trofi yang diberikan oleh pelatih tersebut kepada tim yang dibesutnya. Dalam hal ini, tentu nama-nama seperti Herbert Chapman, Alex Ferguson, hingga Jose Mourinho masuk dalam daftar.
Namun, ada juga pendapat lain yang menilai bahwa pantas atau tidaknya seorang pelatih disebut maestro bukanlah dari berapa banyak gelar yang berhasil ia raih bersama timnya. Melainkan dengan penilaian, apakah pelatih tersebut mampu membuat pemain yang pernah dilatihnya menjadi pelatih yang sama hebat dengan dirinya? Untuk kriteria ini, mantan pelatih tim nasional Italia dan AC Milan, Arrigo Sacchi, sangat ideal untuk disebut sebagai maestro. Mantan anak-anak didiknya, dari mulai Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ancelotti, hingga Marco van Basten, berhasil menjadi pelatih-pelatih hebat yang melahirkan banyak gelar bagi klub yang dilatihnya.
Perdebatan mengenai kriteria apa yang layak untuk menilai seorang pelatih maestro atau bukan, agaknya akan sulit menemukan titik temu. Toh sebutan itu juga hanya julukan yang diberikan oleh masyarakat atau penggemar sepakbola, bukan satu penghargaan berupa trofi yang diberikan oleh satu otoritas tertentu yang dalam setiap pemilihannya dibutuhkan kriteria-kriteria yang pasti. Yang jelas, sebutan maestro kerap kali disematkan kepada pelatih atau pemain yang punya peran dan kontribusi hebat, dan sosoknya sangat berpengaruh bagi tim yang dibelanya.
Dan di balik itu semua, ada satu fenomena menarik tentang maestro dalam sepakbola ini. Yaitu bagaimana mereka, para maestro itu, kerap berubah wujud menjadi hantu-hantu tak kasat mata di tim yang pernah dibelanya. Hantu-hantu itu berupa ingatan kolektif tentang kehebatan yang pernah maestro itu berikan di masa lalu untuk tim tersebut — bisa berupa limpahan gelar, permainan yang apik, hingga peran di dalam tim yang sulit tergantikan. Segala kehebatan itu jelas akan membayangi sekaligus membebani generasi-generasi penerus di tim tersebut.
Ada banyak kasus untuk contoh hal ini. Di kalangan pelatih, Bobby Robson yang menggantikan Johan Cruyff sebagai pelatih Barcelona pada 1996-1997, sulit lepas dari bayang-bayang hantu Cruyff yang meninggalkan ingatan hebat bagi publik Barcelona — Cruyff telah berhasil merevolusi cara menyerang Barca pada saat melatih tim Catalan itu . “Cruyff seperti bayang-bayang gelap yang menghantuiku,” sebut Robson satu waktu.
Di kalangan pemain, kita bisa mengambil contoh bagaimana Manchester United kehilangan sosok Ronaldo saat meninggalkan United ke Real Madrid pada 2009. Dikait-kaitkannya beberapa pemain seperti Federico Macheda, Antonio Valencia, Luis Nani, hingga Bebe saat itu sebagai "penerus" Ronaldo, adalah gelagat yang menunjukkan United sulit lepas dari bayang-bayang hantu Ronaldo.
Jauh sebelum Ronaldo menjadi hantu bagi publik Old Trafford, pria Portugal lain sudah lebih dulu menjadi hantu bagi suporter Fiorentina. Pria itu identik dengan nomor 10. Penampilannya yang memukau di lapangan tengah Fiorentina bersama duetnya saat itu, Gabriel Batistuta, begitu sulit dilupakan oleh publik Stadion Artemio Franchi.
Ia dianugerahi dengan teknik olah bola yang mumpuni, kontrol bola yang menawan, kemampuan membangun serangan, serta ketajamannya dalam melihat peluang gol. Saat membela Fiorentina di medio 1990-an sampai awal tahun 2000, ia telah mempersembahkan dua trofi Coppa Italia dan satu gelar Piala Super Italia. Selama tujuh musim di Fiorentina itu, ia selalu menjadi andalan di lapangan tengah La Viola dengan jumlah penampilan sebanyak 276 kali jumlah gol sebanyak 50.
Berkat segala kehebatan yang ditinggalkannya di Artemio Franchi, akan sulit bagi siapa pun yang mengenakan nomor punggung 10 di Fiorentina, untuk lepas dari bayang-bayangnya. Nomor tersebut sangat identik dengannya. Ingatan suporter Fiorentina agaknya akan selalu terpaut padanya ketika melihat nomor tersebut. Berkat kehebatannya pula ia dijuluki sebagai "The Maestro" atau, sebagaimana suporter Fiorentina menyebutnya, "il Maestro Fiorenze". Sang Maestro lapangan tengah itu adalah Rui Costa.
Segalanya Berawal dari Piala Dunia U-21
Rui Costa lahir dengan nama lengkap Rui Manuel Cesar Costa. Ia lahir pada 29 Maret 1972, di sebuah kota bernama Amdora, Portugal. Kota itu terletak di sebelah barat laut Lisbon, dan merupakan salah satu kota terpadat di Portugal.
Perkenalan pertamanya dengan sepakbola adalah ketika ia bergabung dengan tim sepakbola untuk balita bernama Damaia Ginasio Clube. Ketika usianya sudah menginjak lima tahun, Costa masuk tim junior Benfica.
Ketika memulai latihan pertamanya di tim junior Benfica, Costa tak butuh waktu lama untuk memikat perhatian sang pelatih. Dalam waktu hanya sepuluh menit, Costa sudah mampu membuat legenda sepakbola Portugal, Eusebio, yang menjadi pemandu bakat di tim tersebut, terpikat.
Saat itu Costa langsung dimasukkan ke akademi junior Benfica dan menimba ilmu di sana selama 13 tahun. Tahun 1990, ketika usianya menginjak 18 tahun, menjadi pengalaman pertamanya bermain sebagai pemain profesional. Kala itu ia dipinjamkan oleh akademi Benfica kepada sebuah klub bernama A.D. Fafe selama satu musim. Setelahnya, Costa dikembalikan ke Benfica.
Pertandingan final Piala Dunia U-21 pada tahun 1991 menjadi momen yang sangat menentukan bagi perjalanan karir Rui Costa ke depannya. Pasalnya, momen inilah yang bisa dibilang menjadi tempat untuk menguji sekaligus menunjukkan kemampuannya pada dunia. Sebentuk tahapan upacara ritual yang harus dilalui seseorang dalam masyarakat adat untuk meningkatkan kedudukannya di tengah masyarakat — sebuah rite de passage.
Pemain dengan rambut bergelombang sebahu itu ternyata mampu melewati rite de passage-nya dengan sempurna. Ia berhasil mengantarkan Portugal menjadi kampiun di ajang tersebut dengan satu gol yang dicetaknya ke gawang Brasil di pertandingan final.
Terbukti usai melewati tahap itu, karir Costa semakin membaik. Ia kembali ke Benfica dan mulai menjadi pemain reguler di tim itu pada musim 1991/92. Perannya semakin terasa ketika beberapa musim berikutnya ia berhasil membawa Benfica meraih dua trofi, yakni gelar Piala Portugal dan Divisi Pertama Portugal pada 1993.
Kebersamaan dirinya bersama Benfica harus berakhir pada tahun 1994. Ketika itu Benfica dilanda krisis keuangan. Alhasil klub asal Italia, Fiorentina, yang kepincut dengan bakatnya, tidak menemukan kesulitan yang berarti kala memboyong Costa dari Benfica ke Fiorentina. Fiorentina memboyong Costa dari Benfica dengan mahar 6 juta euro.
Di Fiorentina inilah Costa menemukan bentuk permainan terbaiknya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penampilannya di lapangan tengah Fiorentina begitu memukau. Selama tujuh musim ia membela tim dengan warna kebesaran ungu tersebut, Fiorentina berhasil menelurkan tiga gelar.
Namun kendati Costa tengah berada di puncak karir bersama Fiorentina, ia tidak lupa kepada klub tempat ia berasal. Ada satu momen yang cukup emosional baginya, kala Fiorentina bersua dengan Benfica di sebuah pertandingan pramusim, bulan Agustus 1996.
Pertandingan itu digelar di Estadio da Luz, Lisbon. Inilah kali pertama Costa datang ke Lisbon sebagai seorang tamu. Di menit-menit akhir pertandingan tersebut, Costa menerima umpan dari duetnya, Batistuta. Usai menerima umpan itu, ia menggiring bola masuk ke kotak penalti melewati dua pemain bertahan Benfica, Cristavao dan Dimas Teixeira, yang menurut Costa sendiri merupakan sahabatnya. Sesudah Cristavao dan Dimas terlewati, Costa mencetak gol dengan sebuah lob yang indah, mengelabui penjaga gawang Benfica, Michel Preud’homme.
Yang menarik usai mencetak gol tersebut, tak ada selebrasi yang berlebihan dari Costa. Sebaliknya, ia hanya berjalan kembali ke tengah lapangan sembari menutupi wajahnya yang sedikit berlinang air mata. Usai wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir, Costa berlari ke pinggir lapangan, menghampiri pendukung Benfica yang berada di tribun stadion. Sang Maestro lalu membuka jerseynya untuk kemudian dilemparkan kepada pendukung Benfica, lalu bertepuk tangan untuk mereka.
***
Sahabat masa kecil, sebut Milan Kundera dalam novelnya yang berjudul “Identitiy”, adalah cermin yang memantulkan masa silam kita. Teman masa kecil dibutuhkan untuk menjaga keutuhan masa silam, untuk memastikan bahwa diri tidak menyusut, tidak mengerut, bahwa diri tetap bertahan pada bentuknya.
Barangkali kutipan dari Milan Kundera itulah yang bisa melukiskan perasaan Costa saat bersua dengan teman-teman masa kecilnya di Benfica dahulu. Termasuk saat melewati dua sahabatnya, Cristavao dan Dimas Teixeira sebelum membobol gawan Benfica. Inilah pula yang mungkin menyebabkan dirinya berlinang air mata usai mencetak gol. Seperti kata Kundera, Cristavao dan Dimas Teixeira seakan menjadi cermin yang memantulkan masa kecilnya dahulu kala menimba ilmu di Benfica.
Karena bagaimana juga, Benfica adalah tempat segalanya berawal bagi Sang Maestro. Benfica adalah sebuah cermin bagi Costa yang memastikan dirinya tetap utuh pada bentuknya yang semula, walaupun tengah berada di puncak karir bersama Fiorentina. Air matanya usai mencetak gol hingga jersey yang ia lemparkan kepada suporter Benfica usai pertandingan, seakan ingin menegaskan bahwa ia tetap Rui Costa yang dulu. Tidak menyusut, tidak mengerut.
Costa membela Fiorentina sampai tahun 2001. Selanjutnya, AC Milan menjadi pelabuhan berikutnya bagi Sang Maestro. Ia digaet Milan dengan harga yang fantastis dan menjadi pemain termahal yang pernah direkrut AC Milan, yakni dengan nilai sebesar 43,9 juta euro. Dalam lima musimnya bersama Milan, ia mampu memberikan satu gelar juara Serie A, satu trofi Coppa Italia, satu trofi Piala Super Italia, satu trofi Liga Champions, dan satu trofi Piala Super Eropa.
Pada musim 2006/07, Costa pulang kampung ke Benfica dan membela tim masa kecilnya itu selama dua musim. Dengan usia yang semakin menua, Sang Maestro tidak terlalu banyak tampil di Benfica. Dari dua musimnya tersebut, ia hanya tampil sebanyak 67 kali dengan mengemas 11 gol, sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun.
Di balik penampilan hebat dan prestasi yang ia raih bersama klub sepanjang kariernya sebagai pesepakbola, Costa ternyata menyimpan satu keinginan yang gagal terwujud sampai ia pensiun. Keinginan itu adalah membawa tim nasional Portugal meraih gelar di ajang Euro maupun Piala Dunia.
Pada 2004 kesempatan itu terbuka lebar saat Portugal lolos ke babak final Piala Eropa menghadapi Yunani. Namun tim tuan rumah harus menerima kenyataan pahit. Di hadapan publiknya sendiri, mereka kalah dari Yunani di babak final. Portugal gagal menjadi juara; Rui Costa gagal mewujudkan keinginannya.
Sang Maestro tampak sudah lelah mengikuti keinginannya itu. Usai final tersebut ia memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Portugal.



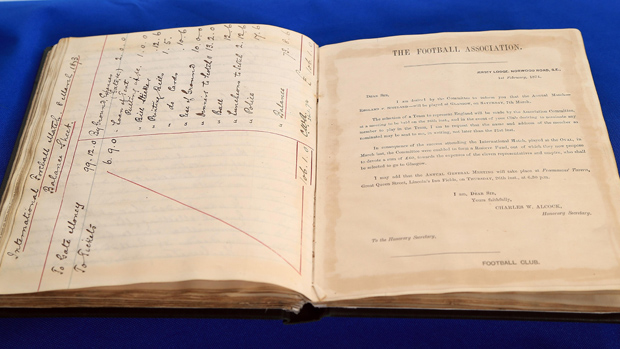






Komentar