Hari itu, 25 Juni 1978, beberapa sipir menyalakan radio dan mencari frekuensi pertandingan final Piala Dunia antara Argentina dan Belanda. Di sisi lain, para tahanan berdesakan dalam sel berukuran 2x2 meter. Selusin manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berebut udara. Mereka warga Argentina yang diculik dan disembunyikan di penjara rahasia atas dasar pandangan politiknya. Petugas menyiksa mereka hingga terluka. Alhasil para tahanan berdesakan dengan darah dan nanah.
Para tahanan politik itu adalah mereka yang mengutuk kediktatoran kejam Argentina di bawah komando Jorge Rafael Videla, yang menyerang rakyat secara fisik maupun psikis. Ada perasaan aneh ketika harus mendukung tim nasional yang dijadikan alat pelanggeng kekuasaan. Mereka sedih saat sepakbola digunakan rezim sebagai senjata lain dalam perang terhadap rakyat mereka sendiri.
“Saya pikir, Piala Dunia 1978 adalah salah satu luka mendalam bagi warga Argentina.” Kenang Norberto Liwski, eks tapol, kepada ESPN pada 2014. Liwski masih ingat dirinya dipukuli dengan tongkat pada minggu pertama berada di kamp tahanan. Setelah dipukuli, ia digantung di sel. Liwski mengaku buah zakarnya dihajar, kulit telapak kakinya dicungkil, dan lubang pantatnya dimasuki tongkat listrik. Begitu alat siksa dinyalakan, ia menjerit seperti binatang.
Ketika pembukaan Piala Dunia 1978 hendak diselenggarakan, para tahanan dipindah ke kamp tahanan lain. Liwksi masih ingat gegap-gempita warga menyambut Piala Dunia. Dari dalam sel, ia melihat baliho besar bertuliskan: “we are human and we are right”. Hati Liwksi seketika tercabik membaca slogan bernadakan humanisme itu.
Propaganda junta militer Argentina terbukti berhasil. Rakyat terbelah jadi dua kubu: yang membenci Piala Dunia dengan yang tidak. Selama 40 tahun Argentina hidup di bawah bayang-bayang Brasil dan Uruguay dalam hal prestasi sepakbola. Untuk itulah rezim Videla menggunakan Piala Dunia sebagai momen meningkatkan harga diri bangsa.
Sebelum pertandingan semifinal yang mempertemukan Argentina dengan Peru, Videla sempat berkunjung ke ruang ganti tim lawan. Penjaga gawang Peru saat itu bernama Ramon Quiroga, yang kebetulan lahir di Argentina. Ada desas-desus bahwa ia disuap. Meski ia membantah tuduhan tersebut, faktanya enam gol bersarang ke gawangnya. Beberapa tahun setelah pertandingan itu, jurnalis mengungkap ada bantuan ke Peru senilai lebih dari 50 juta dolar AS. Maka tidaklah heran jika banyak kalangan berpikir bahwa rezim Videla telah “membeli” gelar juara Argentina.
Jauh sebelum Piala Dunia 1978 digelar, PSSI-nya Belanda melakukan konferensi pers yang menyatakan akan meninjau ulang keikutsertaan mereka di Argentina. Hal itu tak lepas dari gejolak politik di Argentina yang dikhawatirkan akan menodai maruah pertandingan sepakbola. Namun nyatanya pasukan De Oranje tetap berangkat meski tanpa Johan Cruyff, gelandang andalan mereka. Sampai akhir hayatnya, Cruyff menolak bahwa dirinya tidak ikut ke Argentina karena perbedaan pandangan politik.
Jadwal pertandingan Piala Dunia 1978 juga tak luput dari sorotan. Sementara kesebelasan lain bertanding pada siang dan sore hari, Tim Tango selalu bermain pada malam hari. Hal itu jadi keuntungan karena mereka sudah tahu lebih dulu hasil pertandingan para lawan.
Namun sejarah tidak bisa diubah. Kejahatan hak asasi manusia yang dilancarkan rezim Videla, juga tuduhan pengaturan skor, tidak lantas membuat Argentina kehilangan “bintang” penanda gelar juara mereka—gelar juara Piala Dunia pertama Argentina. Piala Dunia di Argentina adalah pelajaran paling berharga tentang betapa buruknya sepakbola jika disusupi kepentingan politik.








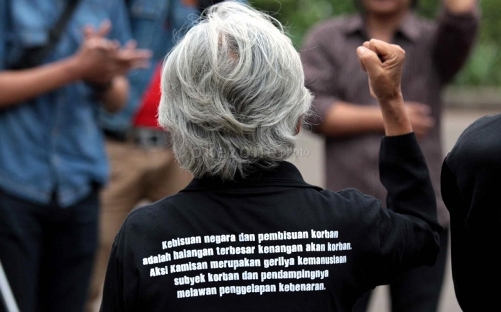

Komentar