Oleh: Abdal A. Choirozzad
Sepakbola muncul pertama kali sebagai sebuah permainan, sebelum berevolusi menjadi industri dan mata pencaharian. Marwah sebagai permainan itulah yang kemudian menegaskan pandangan filsuf Johan Huizinga bahwa sejatinya manusia itu homo ludens (entitas bermain). Bagi saya, memori bermain sepakbola semasa kecil adalah pengalaman tepermanai. Kawan-kawan saya pun sepakat dengan hal itu.
Tapi, beranjak dewasa saya mendapati bahwa kita mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Secara berangsur-angsur, rutinitas bermain sepakbola mulai terpinggirkan. Tentu, kesibukan bukanlah faktor tunggal. Alasan lainnya bisa saja lapangan yang sudah berubah rupa jadi gedung perusahaan. Namun, walaupun sepakbola mulai mengalami pergeseran dari permainan menjadi sekadar tontonan, saya masih memiliki gairah yang tinggi jika ada yang menyinggung soal sepakbola.
Dugout: Informasi terkini sepakbola dunia
Di samping sepakbola, kesusastraan adalah budaya lain yang juga saya gandrungi. Tidak hanya genre sepakbola, rak buku saya juga diisi oleh buku-buku lain yang bahkan tiada kaitannya dengan olahraga. Bagaimanapun juga, saya suka tersentuh dengan penulis-penulis prolifik yang suka menyinggung sepakbola dalam karyanya, walau hanya secuil dan sambil lalu.
Dalam novel Sampar Albert Camus, misalnya, stadion sepakbola mengalami pengalihfungsian jadi suaka untuk para korban terdampak wabah mematikan. Adegan itu memang sekelebat dan jika dinegasikan pun tidak akan secara signifikan mengubah alur cerita. Namun, bagi saya itu bagaikan menemukan mata air di tengah gersangnya padang pasir.
Belakangan, saya mengetahui Camus adalah seorang penulis cum pencinta sepakbola. Sebelum meniti karier sebagai pujangga Camus adalah lelaki yang rajin sekali bermain sepakbola. Posisinya sebagai seorang kiper. Celakanya, kebiasaan itu harus terhenti ketika sang penulis mulai mengidap penyakit tuberkulosis pada usia 16 tahun. Adapun identitasnya sebagai pencinta sepakbola tidak pudar dan bahkan mencapai titik kulminasi pada tahun 1957, manakala ia terpilih sebagai pemenang penghargaan Nobel Kesusastraan, sebuah ajang prestisius dalam kalangan sastrawan.
Ketika berbincang dengan seorang wartawan tentang penghargaan yang baru diraihnya itu, Camus menarik perhatian publik. Jika pemenang penghargaan biasanya diinterviu dalam ruangan yang penuh keglamoran, Camus justru melakukannya secara kasual di tengah keriuhan stadion sepakbola (kesebelasan Racing Club de Paris vs kesebelasan Monaco).
Dalam satu momen, Racing Club de Paris kebobolan gol setelah si kiper tergelincir dan melakukan blunder. Wartawan menyinggung soal itu. Bak sedang melakukan advokasi, Camus dengan terus terang berkata, “Jangan menyalahkannya (kiper). Jika kau berada di antara tiang gawang, maka kau akan menyadari betapa sulitnya menjadi kiper.”
Rasanya tidak lengkap apabila kita menyoal sepakbola dan sastra tanpa memanggil sosok bernama Orhan Pamuk, yang juga pernah dianugerahi Nobel Kesusastraan circa 2006. Seorang Turki yang piawai dalam menulis ini juga memiliki hobi menonton sepakbola. Beberapa pamannya ada yang mendukung kesebelasan Galatasaray, meski juga ada beberapa yang menaruh peruntungan pada Besiktas.
Ayahnya Pamuk sedikit berbeda karena mendukung kesebelasan Fenerbahce. Perlu digarisbawahi, setidaknya hingga abad ke-20, klub sepakbola dukungan merupakan sesuatu yang diturunkan dari satu ke lain generasi. Setara dengan warisan, marga, atau aliran kepercayaan. Maka dari itu, Pamuk dengan bangga mendaku diri sebagai penggemar Fenerbahce garis keras.
Menjelang pagelaran Euro 2008, majalah Jerman Der Spiegel berkesempatan untuk mewawancarai Pamuk. Percakapan itu mencakup banyak topik, dari potensi timnas Turki hingga bagaimana pendapat Pamuk soal itu. Kecintaannya terhadap sepakbola terlukis dari bagaimana dia mengaku masih bisa menyebutkan daftar susunan pemain Fenerbahce pada tahun 1959. Tidak tanggung-tanggung, ia mampu mendeklamasikan nama para pemain laiknya bait-bait puisi. Romantis, bukan?
Pada puncak kesuksesannya sebagai penulis, Camus tidak bisa tidak seolah menjlentrehkan betapa sepakbola adalah sesuatu yang intrinsik dalam hidupnya. Hal serupa juga dilakukan oleh Pamuk. Bagi saya jelas, ini menegaskan satu hal bahwa sepakbola dan kesusastraan adalah dua hal yang secara jukstaposisi dapat berkelindan, berkawin silang, dan bahkan bermesra-mesraan.
Terus terang saja, saya sudah jarang bermain sepakbola. Kadang, saya rindu menyarangkan bola ke gawang lawan untuk kemudian merayakannya bersama teman-teman. Hari-hari ini lapangan di daerah rumah saya sudah berubah bentuk jadi proyek gedung. Setiap melewatinya, saya hanya bisa melengos dengan berharap tidak larut dalam nostalgia yang tak berkesudahan.
Untuk itulah, saya gembira setiap kali menemukan sepakbola bukan hanya di stadion atau tayangan televisi, melainkan juga di dalam diri seorang sastrawan. Dan jika ada yang terheran-heran kenapa orang bisa tergila-gila dengan sepakbola, saya hanya bisa meminjam kata-kata dari Pamuk, “It (football) is like religion. There is no why.”
*Penulis adalah seorang mahasiswa yang aktif di media sosial melalui akun @choirozzad
**Tulisan ini merupakan hasil kiriman penulis melalui kolom Pandit Sharing. Segala isi dan opini yang ada dalam tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis.





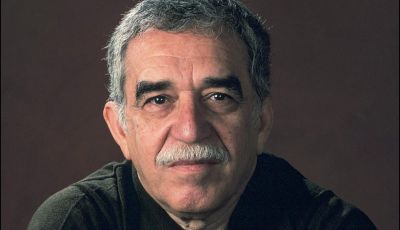
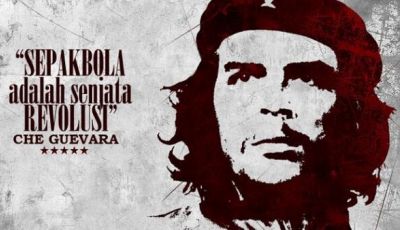



Komentar