Oleh: Ramzy Muliawan
Salah satu debat klasik dalam leksikon sepak bola Indonesia, atau juga negara-negara dengan sepak bola yang berkembang lain, adalah bagaimana seharusnya pembibitan pemain muda dijalankan. Tepatnya, pada siapa tugas melatih, membimbing, dan mengarahkan mimpi-mimpi mereka dibebankan: sekolah atau klub?
Saat ini di Indonesia pada umumnya pembinaan level muda dijalankan oleh sekolah-sekolah sepak bola, atau lazim dipanggil SSB. Entitas ini beroperasi layaknya klub sepak bola pada umumnya: punya lapangan sendiri, misalnya, dengan fasilitas untuk menunjang latihan dan pembinaan. Para pencari bakat merekrut talenta-talenta muda dengan mengiming-imingi kesempatan bermain di klub profesional dengan memanfaatkan jaringan dan hubungan mereka.
Sekolah semacam ini umumnya dimiliki oleh swasta, baik itu dijalankan oleh klub lokal, mantan pemain legenda, atau bahkan klub asing. Mereka yang mengikuti dunia sepak bola Indonesia tentu tak asing dengan SSB berlabel international atau academy di belakangnya, menjanjikan pelatih asing berpengalaman beserta fasilitas mewah nan lengkap.
Tetap saja, pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia masih belum bisa mendongkrak kualitas klub-klub lokal maupun tim nasional. Kalau sudah begitu, maka pertanyaannya biasanya cuma satu: kemana negara?
Mungkin kita bisa mengambil tunjuk ajar pada Amerika Serikat. Meskipun tak terkenal sebagai adidaya sepak bola, Negeri Paman Sam ini memiliki sistem pembinaan atlet muda yang patut dicontoh. Pada olahraga populer seperti American football, bola basket, baseball, dan hoki, pembinaan atlet dimulai pada level Sekolah Menengah Atas, berlanjut pada tingkat perguruan tinggi, sebelum masuk ke dunia profesional. Sistem pembinaan berjenjang seperti inilah yang seharusnya digunakan oleh sepak bola Indonesia.
Boleh dibilang SMA di Amerika benar-benar serius dalam mengurus olahraga. Sebuah SMA negeri bisa menghabiskan ribuan dolar tiap tahun pelajaran untuk membiayai tim olahraga mereka. Contohnya di sekolah tempat saya ditempatkan di Indianapolis, Indiana, Athletic Office adalah bagian integral dari administrasi sekolah.
Terdapat sembilan belas program olahraga yang dimainkan pada musim-musim yang berbeda. Basket dan renang, misalnya, adalah olahraga musim dingin, sedangkan American football, bola voli, dan cross country dimainkan pada musim semi. Fasilitas yang disediakan terbilang cukup baik, mulai dari kolam renang dalam ruangan, empat macam lapangan rumput, sampai gym dan ruang angkat berat.
Menurut data National Federation of State High School Associations, hampir 7,8 juta siswa SMA di Amerika Serikat berpartisipasi dalam satu atau lebih macam olahraga pada tahun 2013. Data lain oleh ESPN menunjukkan bahwa jumlah pada tingkat umur 6 sampai 17 tahun justru lebih besar lagi, mencapai 21.47 juta orang pada tahun yang sama.
Public School Athletic League, liga olahraga sekolah menengah terbesar di Amerika, menghabiskan sekitar 27 juta dolar per tahun untuk membiayai 45,000 atlet pelajar di ratusan sekolah di New York City. Itu setara Rp 3,5 miliar; sebagai perbandingan, anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk tahun 2016 mencapai Rp 605 miliar.
Pembinaan di level sekolah menengah tak terputus setelah mereka lulus. Masih ada jenjang lain: olahraga tingkat perguruan tinggi. Untuk Divisi I dan Divisi II NCAA, liga olahraga mahasiswa yang paling populer, setiap tahunnya tersedia sekitar 138.000 beasiswa atletik.
Selain menjadi sumber kebanggaan, perguruan tinggi biasanya menangguk rezeki yang tak sedikit dari negosiasi hak siar, sponsor, dan kesepakatan komersial lain. 65 universitas terbesar di NCAA menangguk tak kurang dari 6.3 miliar dolar pada musim 2014-15.
Setelah itu, barulah hukum besi alam mulai berlaku. Dari hampir setengah juta pemain tingkat universitas yang tergabung pada tiga divisi di NCAA, kemungkinan untuk menjadi pemain profesional adalah sekitar 1.6% untuk American football, 1.1% untuk bola basket, dan 9.7% untuk baseball.
Penggemar NBA tentulah familiar dengan sistem draft setiap tahunnya, yaitu sistem ketika klub memilih pemain muda potensial untuk direkrut dari tim perguruan tinggi; sebut saja Shaquille O’Neal dari Louisiana State, Michael Jordan dari University of North Carolina, atau Kevin Durant dari University of Texas at Austin.
Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa sistem pembinaan a la Amerika Serikat ini perlu diterapkan di sepak bola Indonesia: uang yang melimpah, pembinaan yang berterusan, dan jaminan pendidikan.
Pertama, olahraga adalah sumber emas yang tak tertanggungkan. Bila dikelola dengan benar, bahkan pertandingan sepak bola tingkat SMA sekalipun bisa menjadi sumber dana untuk pembinaan. Di Amerika Serikat, hak penamaan stadion dan hak siar pertandingan adalah tumpuan utama SMA dan universitas untuk mendanai program atletik mereka.
Fenomena ini dimulai pada tahun 1980an ketika media lokal, termasuk ESPN, mulai menanamkan investasi ke level sekolah, terutama untuk American football. Sponsor dan bantuan dari pihak luar bisa mengurangi ketergantungan sekolah terhadap dana dari pemerintah.
Seperti yang terjadi di sekolah saya sendiri, sekolah berhasil mengamankan kesepakatan dengan sebuah grup otomotif setempat seharga 500.000 dolar untuk renovasi stadion American football, pembangunan pusat latihan, dan perluasan lapangan. Dengan gantinya, perusahaan tersebut mendapatkan hak penamaan selama sepuluh tahun.
Bila diterapkan di Indonesia, faktor uang ini bukan saja akan membantu mendongkrak kualitas pembinaan pelatih muda, tetapi bisa saja membantu menyaring bakat-bakat muda potensial yang terpinggirkan oleh SSB mahal berpredikat mentereng akibat masalah biaya. Buat apa membayar klub asing berjuta rupiah bila SMA negeri bisa menyediakan fasilitas setara, atau bahkan lebih?
Selanjutnya, sistem pembinaan berjenjang ini menguntungkan klub profesional itu sendiri. Berbeda dengan lazimnya tim olahraga Eropa, tidak ada yang namanya Denver Broncos U21 atau LA Galaxy U15. Ketika Phil Jackson merekrut Michael Jordan untuk Chicago Bulls, sang pelatih tak merekrut bakat mentah seperti ketika seorang Lionel Messi tiba di Barcelona.
Jackson merekrut seorang pemain yang sudah matang ditempa oleh kompetisi tingkat SMA dan universitas, atau bahkan pernah jadi juara nasional, seperti pada kasus Jordan yang menjuarai divisi nasional NCAA bersama University of North Carolina Tar Heels. Klub tidak membuang-buang uang untuk membesarkan seorang pemain profesional selama sepuluh tahun seperti akademi tim Eropa.
Sebaliknya, setiap tahun mereka tinggal memilih bakat-bakat segar dengan pengalaman cukup. Tidak akan ada yang namanya bintang yang meredup atau wonderkid yang tersisih, karena sistem yang ada hanya akan mengakomodasi yang terbaik dan menyisihkan yang kurang baik.
Seorang Freddy Adu, Anthony Vanden Borre, atau Ibrahima Bakayoko takkan bisa memanjat naik sistem meritokrasi seperti ini, apalagi bermain buat tim profesional. SMA memasok pemain untuk universitas; universitas memasok pemain untuk tim profesional.
Terakhir, tak akan ada lagi dilema lapangan bola atau ruang kelas. Masalah klasik yang kerap muncul, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain, adalah olahraga dan pendidikan kerap kali tak bisa berjalan bersama, segendang-sepenarian. Kita tentu ingat bintang-bintang sepak bola dunia yang meninggalkan bangku kelas demi mengejar mimpi mereka di lapangan hijau.
Namun banyak pula kasus pemain yang sudah terlanjur medioker lalu kemudian bingung ketika hendak banting setir dari menggocek si kulit bundar, sering kali karena dunia di luar stadion masih begitu menghargai gelar sarjana. Hal ini takkan terjadi jika sepak bola Indonesia menerapkan sistem ala Amerika: atlet bermain untuk tim SMA atau perguruan tinggi sementara tetap masuk kelas dan mengerjakan tugas. Seperti yang ditulis oleh Kai Sato untuk The Huffington Post:
"Berkat adanya olahraga di tingkat SMA, anak-anak Amerika dapat menjadi pelajar dan atlet sekaligus. Jika Anda tidak berbakat pada usia yang sangat muda dan mampu secara finansial untuk bermain, masa depan Anda di olahraga tersebut tidak akan cerah. Michael Jordan, yang tidak berbakat dalam bermain basket sampai akhir masa SMA-nya, tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Michael Jordan."
Logis, bukan?
Sebenarnya, sepak bola Indonesia sendiri sudah mengarah ke jalan yang tepat. Terwujudnya Liga Pelajar Indonesia adalah langkah yang cukup positif, terutama dengan adanya kategorisasi universitas dan SMA dalam kompetisi tersebut. Namun, untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan untuk bermain, membuat liga saja mungkin tidak akan cukup.
Sekolah, baik negeri maupun swasta, seharusnya memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dan pamor yang lebih dibanding SSB yang bisa saja dibongkar-pasang dalam satu malam. Dalam hal ini, baik PSSI sebagai induk semang sepak bola nasional maupun pihak swasta lain sepatutnya berperan lebih banyak dan beraksi lebih berani.
Pada akhirnya, masa depan sepak bola Indonesia tetaplah bergantung pada para pemegang kepentingan: PSSI, pelatih, pemain, klub, dan pendukungnya. Namun bila kita benar-benar ingin memperbaiki kualitas sepak bola kita, pembinaan pemain muda adalah sasaran paling tepat untuk memulai.
Maka, untuk memastikan para pemain muda yang berlaga dengan lambang Garuda di dada benar-benar layak mendapatkannya, barangkali tak ada salahnya untuk mendongak sedikit ke timur, ke Negeri Paman Sam, untuk mengambil sedikit tunjuk dan ajar.
Penulis adalah jurnalis dan fotografer, mendukung Semen Padang dan mengagumi Juventus. Saat ini tengah mengikuti program pertukaran pelajar selama satu tahun di Indianapolis, Amerika Serikat. Biasa berkicau di @ramzymuliawan.
foto: leemjelias.com


/Olahraga%20di%20Amerika.png)




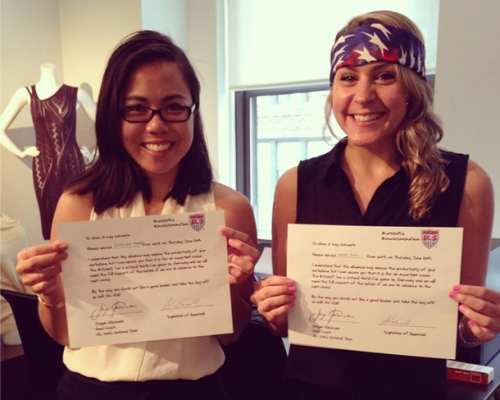


Komentar