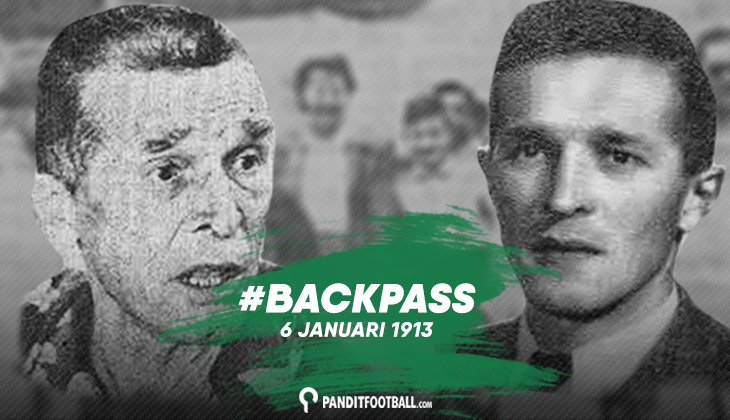Diakui atau tidak, era 1950-an bakal dikenang sebagai salah satu periode termanis dalam sejarah sepakbola Indonesia. Alasan-alasan yang mendasari klaim tersebut cukup banyak.
Pertama, Tim Nasional Indonesia mampu menembus semifinal Asian Games 1954 di Manila walau akhirnya keok di laga perebutan medali perunggu melawan Myanmar. Kedua, Indonesia sukses menahan imbang salah satu kesebelasan top pada masa itu, Uni Soviet, dengan skor 0-0 di Olimpiade Melbourne 1956. Dan ketiga, Indonesia menggondol medali perunggu di Asian Games 1958 di Tokyo.
Sungguh luar biasa, bukan?
Maka tak perlu heran bila kisah gilang gemilang itu masih awet direproduksi sampai hari ini. Sebuah momen fantastis, memunculkan euforia, dan rasa gembira yang tak terkira. Berkat capaian itu juga, Indonesia disebut-sebut sebagai Macan Asia. Predikat bombastis dan menjanjikan kala itu muncul sebab kiprah serdadu Garuda dipandang setara dengan kekuatan utama Asia semisal Iran, Jepang, dan Korea Selatan.
Keberadaan pemain-pemain berkualitas semisal Kwee Kiat Sek, Maulwi Saelan, Ramang, Rukma Sudjana, dan Wowo Sunaryo, selalu disebut sebagai kunci bagusnya performa Indonesia di tiga kejuaraan tersebut. Namun di atas itu semua, publik takkan ragu menyebut pelatih berkebangsaan Yugoslavia, Antun "Toni" Pogacnik, sebagai sosok watak di balik lesatan sepakbola Indonesia pada era tersebut.
Toni Pogacnik lahir di Livno (saat itu bagian dari Austria-Hungaria, saat ini bagian dari Bosnia-Herzegovina), 6 Januari 1913. Dia didatangkan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada rezim kepemimpinan Maladi.
Pogacnik berkontribusi masif atas perubahan yang terjadi dalam sepakbola Indonesia. Alih-alih datang layaknya bos dengan gaya "petantang-petenteng" seraya berteriak memberi instruksi kepada pemain-pemainnya dari pinggir lapangan, Pogacnik lebih suka turun langsung ke lapangan buat melatih dasar-dasar permainan sepakbola kepada anak asuhnya; mulai dari menendang, mengumpan, menyundul, mengontrol bola, sampai melakukan tekel.
Antun Pogacnik sadar jika kemauan keras pemain-pemain Indonesia tak dibarengi dengan teknik olah bola mumpuni dan kecerdasan dalam bermain. Hal itulah yang coba dibenahi Pogacnik.
Sosok berperawakan kutilang (kurus-tinggi-langsing) ini juga fokus terhadap pengembangan pemain muda. Pogacnik mengerti bahwa masa depan sepakbola ada di kaki pemain-pemain belia. Oleh karena itu, dirinya pun mencurahkan segenap perhatiannya terhadap hal ini. Benar saja, pesepakbola muda yang digembleng Pogacnik sedari awal datang ke tanah air, bertransformasi jadi andalan timnas selama kurang lebih satu dekade.
Tak berhenti sampai di situ, Pogacnik yang semasa aktif bermain pernah membela Timnas Yugoslavia dan Kroasia, amat kondang sebagai pelatih yang acap menggembleng karakter pemainnya. Dia selalu menekankan kepada anak asuhnya supaya bermain dengan jujur, tidak bertindak curang, bersifat ksatria, dan disiplin. Meski terlihat sepele, apa yang ditekankan Pogacnik ini menghadirkan pengaruh yang amat besar dari sisi psikologis.
Namun sial, potensi Indonesia yang tengah meletup-letup di kancah sepakbola akibat polesan Pogacnik, luluh lantak seketika gara-gara pengkhianatan pemain-pemainnya sendiri.
Usai meraih medali perunggu di Asian Games 1958, keseriusan Pogacnik, PSSI, dan pemerintah untuk menelurkan timnas yang semakin tangguh terus membubung. Berbagai upaya mereka lakukan demi performa gemilang di Asian Games 1962 yang diselenggarakan di Jakarta. Tanpa ragu, Indonesia memasang target juara dalam kejuaraan tersebut.
Berlaga di depan publik sendiri tentu melipatgandakan motivasi dan kepercayaan diri Indonesia. Akan tetapi, skandal suap yang berputar di kalangan pemain justru menjerat mereka sehingga tampil apa adanya dan tanpa gairah. Hasilnya pun bisa ditebak, skuat Garuda gagal total akibat rontok di penyisihan grup.
Usut punya usut, skandal suap yang populer dengan sebutan Skandal Senayan 1962 itu dilakukan secara langsung oleh bandar-bandar judi kepada penggawa timnas. Entah bagaimana caranya, banda-bandar itu memiliki akses untuk bertemu secara langsung dengan para pemain di mes timnas. Mereka pun mengiming-imingi uang berjumlah lumayan sehingga iman para pemain goyah.

Baca selengkapnya: Skandal Senayan 1962 Libatkan 10 Pemain Timnas
Pada masa itu, bayaran yang diterima pemain timnas hanya sekitar 25 rupiah per harinya. Bukan jumlah yang kelewat kecil, tapi tetap saja minimalis, terlebih untuk pemain yang sudah berkeluarga. Padahal, mereka sering meninggalkan keluarga tercinta demi berlatih dan bertanding dengan seragam Indonesia.
Menurut pengakuan Wowo, keterlibatan para pemain di dalam skandal suap itu lekat kaitannya dengan faktor ekonomi. Bayaran yang rendah, bikin mereka sulit menampik tawaran segepok uang dari para bandar judi.
"Honor memperkuat timnas hanya cukup untuk biaya perjalanan Bandung-Jakarta. Kalau ada sisa, cuma bisa digunakan membeli dua butir telur atau sabun. Kondisi miris itulah yang memaksa kami melakukan hal tidak terpuji itu", terang Wowo seperti dilansir dari detikSport.
Mengetahui bahwa perilaku anak asuhnya menyimpang dari apa yang ia tanamkan, Pogacnik kecewa sekaligus marah besar. Peristiwa itu bak sebuah tikaman keras di punggungnya.
Imbas dari kasus ini sangat terasa betul bagi Pogacnik. Tim yang ia banggakan dan bina selama bertahun-tahun harus hancur lebur dalam hitungan hari. Dari 30 pemain yang mengikuti training camp, 10 di antaranya harus pulang karena aib memalukan ini dan enam pemain lainnya juga dipulangkan karena soal teknis yang masih belum jelas. Pogacnik sangat gusar dan hancur karena peristiwa ini.
Tantangan sekaligus kesulitan membentang di depan matanya. Asian Games 1962 yang jadi target utama sudah di depan mata, tinggal 5 bulan lagi, tapi pemain yang tersisa tinggal 14. Upaya keras dan semampunya dari pelatih asal Yugoslavia itu tak menuai hasil seperti yang diharapkan. Boro-boro meraih emas, Indonesia bahkan gagal lolos dari fase grup.
Hatinya hancur berkeping-keping dan membuatnya ingin melepas jabatannya sebagai Pelatih Indonesia sesegera mungkin, tetapi ditolak kubu PSSI. Pogacnik akhirnya benar-benar berhenti menyandang status pelatih timnas di tahu 1963 usai dihantam cedera lutut.
Selama bertahun-tahun mencari bakat di pelosok negeri dan melatih mereka dengan keseriusan tinggi, Pogacnik sangat paham kalau anak asuhnya sudah mencapai standar internasional. Namun peristiwa kelam itu seolah jadi salah satu penanda bahwa sepakbola Indonesia enggan maju dan jadi lebih baik. Indikatornya sederhana saja, selain maraknya kasus-kasus suap dalam sepakbola nasional, prestasi timnas pun begitu stagnan.
Jangankan meraih medali lagi di ajang sekelas Asian Games, sekadar merebut medali emas di South East Asia (SEA) Games atau trofi juara di Piala AFF saja tak pernah mampu diwujudkan selama hampir tiga dekade pamungkas. Faktor penyebab paceklik gelar itu sudah pasti beragam, mulai dari kualitas timnas yang buruk hingga tata kelola yang amburadul dari PSSI sebagai pemangku kekuasaan.
Setelah gagal di Asian Games 1962, Pogacnik kemudian membesuk para tersangka yang mendekam di penjara kantor Polisi Militer, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Dia menangis, tapi tetap saja tak mampu membalikkan keadaan. Barangkali, itulah salah satu derai air mata paling tragis dalam sejarah Indonesia yang harus mengucur karena aib memalukan skandal suap.
Mungkin saja, dosa masa lalu Indonesia kepada Pogacnik yang telah mencurahkan segenap kemampuannya bagi perkembangan sepakbola di negeri ini, yang membuat Indonesia sulit berprestasi.