Pengantar untuk dan sebelum menikmati laga pamungkas Copa America 2015
[1]
6 September 1995, di Stadion Wembley, berlangsung laga uji tanding antara Kolombia melawan tuan rumah Inggris. Skor berakhir imbang tanpa gol. Tetapi ada satu momen yang membuat laga yang sebenarnya biasa saja itu menjadi penting: Rene Higuita, kiper Kolombia, melakukan aksi akrobatik yang dikenal hingga sekarang. Meski Inggris sangat mendominasi, tapi gawang Kolombia tetap perawan. Higuita bermain gemilang di laga itu. Puncaknya ketika Jamie Redknapp membuat percobaan mencetak gol dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke arah Higuita. Alih-alih menangkap, ia malah mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan balik sambil tetap menghadap ke depan. Aksi itulah kemudian yang melambungkan namanya, tendangan kalajengking. Momen itu memperlihatkan betapa Higuita memang lebih suka melakukan hal beresiko. Apa yang sebenarnya mudah, dengan sadar ia bikin jadi lebih sulit. Aksi Higuita itu memperlihatkan juga betapa dia memang seorang gila yang kadang tak bisa dihitung kapan nalarnya bekerja dan kapan naluri kegilaannya mengambil-alih. Bandingkan dengan momen ketika Gordon Banks, kiper Inggris, ketika melakukan penyelamatan monumental di Piala Dunia 1970. Sundulan Pele yang sangat sulit dijangkau karena lajunya sangat deras dan sempat memantul ke tanah, sehingga niscaya tak ada yang berani bertaruh sundulan itu tidak akan menjadi gol, toh dapat ditepis oleh Banks dengan refleks dan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada yang aneh dalam aksi Banks itu. Aksi itu gabungan antara atletisisme dan refleks yang dilatih dengan keras, kontinyu dan tanpa henti. Aksi Banks itu seperti kebalikan dari apa yang dilakukan Higuita: apa yang (tampaknya) sulit bisa dilakukan dengan (seperti) begitu mudah. Aksi Banks adalah tindakan logis, terukur, rasional; berbeda dengan aksi Higuita yang sulit dinalar, tidak logis dan tak terukur resikonya. Orang boleh beranggapan bahwa aksi Higuita itu toh itu hanya laga uji tanding. Belum tentu dia berani melakukan kegilaan macam itu di laga-laga genting. Untuk argumen itu, kita hanya perlu mengingat aksi gila Higuita di perdelapanfinal Piala Dunia 1990 saat Kolombia berhadapan dengan Kamerun. Di babak perpanjangan waktu, ketika Kamerun baru saja mencetak gol, dan unggul 1-0, Kolombia jelas butuh bermain agresif untuk menyamakan kedudukan. Tapi juga tetap harus bermain aman karena jika kebobolan satu gol lagi maka tamatlah riwayatnya. Tapi apa yang terjadi? Dalam situasi yang aman, bukan darurat, Higuita tiba-tiba naik mendekati garis tengah. Dia mengambil bola liar. Lalu saling mengoper dengan seorang rekannya. Ketika bola tiba di kakinya lagi, ia malah mencoba meng-keeping bola, dan dampaknya adalah: Roger Milla datang merebut bola. Mudah saja Milla mencetak gol keduanya di laga itu. Kiper di laga penting dan situasi genting sangat berhati-hati biasanya. Jika pun mau maju, itu pun berebut bola di momen tendangan sudut, itu pun ketika waktu sudah memasuki injury time. Lha ini? Babak perpanjangan waktu kedua baru saja dimulai, tapi Higuita sudah edan-edanan naik ke tengah lapangan, melakukan operan satu dua, dan bahkan mencoba men-drible bola. Kolombia pun tersingkir 1-2. Higuita, di kemudian hari, menyebut blunder itu sebagai "sebuah kesalahan sebesar rumah" (ungkapan yang asyik, bukan?).
Selengkapnya tentang Tendangan Kalajengking René Higuita
Kegilaan, atau aksi-aksi yang tidak masuk akal karena konyol, berlebihan atau aksi yang tidak logis karena menyulitkan diri sendiri, memang menjadi ciri khas Higuita. Coba simak kata orang Inggris, tepatnya respons pelatih Inggris saat itu, Terry Venables: "Saya tak pernah menyaksikan hal luar biasa seperti itu sebelumnya. Kami tidak akan mengajarkan kiper saya hal seperti itu. Biarkan dia (Higuita) saja yang melakukannya, karena hanya dia yang sanggup melakukan hal itu." Apa yang dilakukan Higuita, juga komentar Venables, buat saya, cukup bisa dijadikan pintu masuk untuk memahami betapa hal-hal gila, aneh dan fantastis memang merupakan hal lazim di wilayah Amerika Selatan -- termasuk dalam sepakbolanya.
[2]
Pablo Escobar selalu menyodorkan dua pilihan: plata o plomo, silver or bullet, perak/uang atau peluru? Pilihan itu bukan hanya disodorkannya kepada jaksa, polisi, hakim, politisi atau para pejabat pemerintah, tapi juga pada siapa pun yang berurusan dengannya. Juga kepada penduduk kota Medellin. Kepada mereka yang miskin, Pablo memberikan secara cuma-cuma perumahan dan pendidikan serta lapangan. Kepada mereka yang coba menghalangi langkahnya, selalu ada stok peluru yang siap dimuntahkan kapan saja. Jika disodori dua pilihan itu oleh orang yang sangat berkuasa seperti Pablo Escobar, plata o plomo, memangnya kita bisa memilih apa? Jika diminta memilih uang atau peluru, memangnya anda mau pilih yang mana? Plata o plomo tentu bukan hal aneh bagi para pelaku dunia bawah tanah yang bergelap-gelap dengan hukum. Hanya saja, terutama setelah menonton film The Two Escobars[1], pilihan plata o plomo bisa juga dibaca sebagai alegori atas realisme Amerika Latin, juga sepakbolanya, yang penuh paradoks, ironi dan hal-hal absurd yang kerap bertolak belakang. Gabriel Garcia Marquez, salah seorang penulis terbesar Amerika Latin, penulis Kolombia yang masyhur dengan realisme magis dalam novel-novelnya, pernah menggambarkan paradoks Amerika Latin itu dalam pidato yang dibacakannya di depan Komite Nobel yang menganugerahinya penghargaan Nobel Sastra 1981.[2] Kata Marquez:
Reality not of paper, but one that lives within us and determines each instant of our countless daily deaths, and that nourishes a source of insatiable creativity, full of sorrow and beauty, of which this roving and nostalgic Colombian is but one cipher more, singled out by fortune. Poets and beggars, musicians and prophets, warriors and scoundrels, all creatures of that unbridled reality, we have had to ask but little of imagination, for our crucial problem has been a lack of conventional means to render our lives believable. This, my friends, is the crux of our solitude.
Dalam pidatonya di depan Komite Nobel pada 1982, Marquez mengisahkan berbagai kejadian faktual dalam sejarah Amerika Latin yang terlihat seperti fiksi. Salah satunya, kejadian di abad 19, ketika Jenderal Antonio Lopez de Santana, diktator Meksiko, menggelar pemakaman yang sangat megah dan dahsyat hanya untuk menguburkan kaki kanannya yang harus diamputasi.
Itulah kenapa, masih dalam pidato yang sama, El Gabo, demikian ia biasa dipanggil, merasa perlu untuk menjelaskan bahwa kisah-kisah atau karakter-karakter yang ditulisnya bukan hasil olahan imajinasi dan fantasi semata. Segala hal ajaib, sureal, aneh, dan sukar dipercaya yang dia tulis, katanya, semua berasal dari kenyataan-kenyataan yang dilihat, didengar, dan dirasakannya di Amerika Latin.
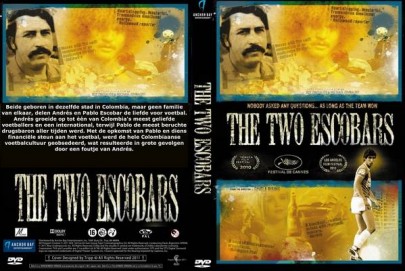 Segala yang kita saksikan dalam film The Two Escobars juga adalah kenyataan: Pablo dan pasukannya yang bersorak-sorai dalam gerilya saat mendengar (melalui radio) timnas Kolombia mencetak gol, para pemain top dunia yang diundang ke kediaman Pablo dan dijemput khusus dengan pesawat pribadi ternyata datang hanya untuk bermain bola dengan Pablo di lapangan bola pribadi di rumahnya,kiper Rene Higuita yang menjelang Piala Dunia 1994 malah mengunjungi Pablo yang sudah diisolir secara terbuka dan terang-terangan sembari melambaikan tangan ke arah wartawan, gedung parlemen Kolombia yang dibom oleh Pablo, pesawat yang dihancurkan pasukan pengawal Pablo lewat peluru kendali, perang kota yang mengerikan karena terbunuhnya Pablo.
Itu semua bukan novel, khayalan, atau cerita dalam film mafioso. Bahkan film-film mafioso pilih tanding seperti trilogi The Godfather atau Goodfellas, Angles With Dirty Face hingga yang puitik seperti Once Upon a Time in America karya maestro Italia Sergio Leone pun tidak menghadirkan tindakan-tindakan spektakuler sebagaimana yang dilakukan kaki tangan Pablo yang saya sebutkan sebagiannya saja di paragraf di atas.
Segala yang kita saksikan dalam film The Two Escobars juga adalah kenyataan: Pablo dan pasukannya yang bersorak-sorai dalam gerilya saat mendengar (melalui radio) timnas Kolombia mencetak gol, para pemain top dunia yang diundang ke kediaman Pablo dan dijemput khusus dengan pesawat pribadi ternyata datang hanya untuk bermain bola dengan Pablo di lapangan bola pribadi di rumahnya,kiper Rene Higuita yang menjelang Piala Dunia 1994 malah mengunjungi Pablo yang sudah diisolir secara terbuka dan terang-terangan sembari melambaikan tangan ke arah wartawan, gedung parlemen Kolombia yang dibom oleh Pablo, pesawat yang dihancurkan pasukan pengawal Pablo lewat peluru kendali, perang kota yang mengerikan karena terbunuhnya Pablo.
Itu semua bukan novel, khayalan, atau cerita dalam film mafioso. Bahkan film-film mafioso pilih tanding seperti trilogi The Godfather atau Goodfellas, Angles With Dirty Face hingga yang puitik seperti Once Upon a Time in America karya maestro Italia Sergio Leone pun tidak menghadirkan tindakan-tindakan spektakuler sebagaimana yang dilakukan kaki tangan Pablo yang saya sebutkan sebagiannya saja di paragraf di atas.
Baca juga:
Tidak ada yang lebih menakjubkan dari kenyataan. Tidak ada yang lebih ajaib dan lebih asing selain kenyataan. Kenyataan, seringkali, lebih menakjubkan dari fiksi. Tak terkecuali dalam sepakbola Amerika Latin. Saya punya beberapa contoh yang pernah saya uraikan dalam esai yang lain: Adakah pemain di dunia ini yang kemampuan dan libidonya dalam menggiring bola melebihi Garrincha? Fiksi atau fakta jika seorang pemain yang sepasang kakinya "rusak" (salah satu kakinya lebih panjang dari yang lain, kaki satunya melengkung ke luar, kaki lainnya melengkung ke dalam) bisa mengobrak-abrik Piala Dunia 1958 dan 1962? Cuma Garrincha, orang Brazil yang setelah main bola akan pergi menemui teman-temannya untuk mabuk sampai pagi, yang bisa melakukannya.[3] Ketika Garrincha meninggal dalam kemiskinan yang mematikan, jenazahnya diarak dan diratapi puluhan ribu orang di Rio de Jeneiro yang merasa kalau mereka telah bergabung dalam tindakan sewenang-wenang membiarkan sang pahlawan mati dengan menyedihkan. Mobil dan orang yang mengantarkan jenazah Garrincha tak ubahnya sebuah parade, atau bahkan sebuah karnaval. Saya pernah membaca laporan dan analisis prosesi pemakaman Garrincha yang disusun oleh antropolog Jose Sergio Leite Lopes. Membaca laporan berjudul "The People`s Joy Vanishes",[4] saya seperti sedang membaca prosesi pemakaman Dr. Juvenal Urbino dalam novel Marquez yang berjudul "Love in the Time of Cholera".[5] Garrincha adalah orang Brasil. Negeri dan bangsa mana selain Brasil yang selalu menghadapi kejadian di mana ada rakyatnya yang bunuh diri tiap kali timnasnya tersingkir dari Piala Dunia? Ini fakta atau fiksi? Bayangkan juga seorang pemain yang tak sengaja melakukan tindakan gol bunuh diri di atas lapangan hijau, akhirnya kemudian benar-bener terbunuh di kehidupan yang sebenarnya? Cuma Andres Escobar yang pernah mengalami betapa tipisnya batas antara pertunjukkan sepakbola dengan kehidupan yang sebenarnya. Di mana kejadiannya? Di Kolombia, tanah kelahiran Marquez, di Amerika Latin. Atau simak kisah Moacir Barbosa, kiper Brasil yang gagal menjaga gawangnya dari pemain Uruguay pada final Piala Dunia 1950. Gara-gara itu, Moacir Barbosa dihukum oleh rakyat Brasil dengan dijauhi, diasingkan, dan dimusuhi sampai masa tuanya. Sejak itu, gawang Brasil tak pernah selamat dari kehancuran tiap kali memasuki Piala Dunia dengan seorang kulit hitam yang menjaga gawangnya. Mitos pun lahir: Brasil tak akan pernah juara jika kipernya bukan kulit putih. Maka ketika Barbosa meninggal dalam keadaan menyedihkan sebagai kambing hitam, penghukumannya seperti sebuah kesakralan yang aneh. Dengan menyitir teori Rene Girard tentang scapegoat, Barbosa menjelma dari seorang kiper menjadi kambing/domba hitam, scapegoat, yang dikorbankan dalam Hari Raya Grafirat seperti diwedarkan Kitab Perjanjian Lama. Maka ketika Barbosa meninggal dalam keadaan menyedihkan sebagai kambing hitam, penghukumannya seperti sebuah kesakralan yang aneh. Dengan menyitir teori Rene Girard tentang scapegoat,[6] Barbosa menjelma dari seorang kiper menjadi kambing/domba hitam, scapegoat, yang dikorbankan dalam Hari Raya Grafirat seperti diwedarkan Kitab Perjanjian Lama. Rivellino melakukan tendangan jarak jauh saat dia melihat kiper lawan, namanya Pirangi, masih berlutut untuk berdoa. Ketika Pirangi selesai berdoa, dia kebingungan sendiri mencari bola yang tidak ada di lapangan. Dia tak sadar bola sudah mendarat di jala gawang yang dijaganya. Esoknya, surat kabar lokal, Folha de Sao Paolo, melaporkan kejadian itu dengan kalimat bersayap yang rasanya cukup surealis dan menggemakan teknik menulis Marquez dalam mengacak dan mempermainkan batas antara fantasi dan kenyataan: "Banyak penonton yang kebingungan....Kiper butuh waktu lebih lama dari orang lain yang ada di stadion untuk tahu bahwa ia telah kebobolan."[7]
Simak kisah lengkapnya: Pelajaran dari Rivellino untuk Kiper: Jangan Kebanyakan Berdoa!
Simak juga dua kisah yang saya baca dari buku "The Beautiful Game: A Journey Through Latin American Football" karya Chris Taylor.[8] Dua kisah ini rasanya cocok untuk menjadi fragmen dalam sebuah novel: Pada 1980, sekelompok gerilyawan berhasil merebut Kedutaan Republik Dominika di Bogota, ibukota Kolombia, tanah kelahiran Marquez. Mereka menggunakan taktik yang hanya bisa dipahami dalam kerangka surealisme Amerika Latin: mereka menyuruh anak-anak main bola, lalu bola ditendang ke dalam kedutaan, lantas mereka minta petugas keamanan kedutaan untuk mengambil bola, dan saat itulah, ketika pintu kedutaan dibuka oleh petugas keamanan, para gerilyawan menyerbu masuk. Lalu simaklah bagaimana tentara Peru menghancurkan para gerilyawan Tupac Amaru yang menyandera orang-orang di rumah Duta Besar Jepang di Lima. Tentara Peru bisa membebaskan 71 orang yang disandera selama 126 hari dengan cara yang cocok dengan kerangka surealisme Amerika Latin: para gerilyawan itu selalu berkumpul untuk bermain bola setiap sore, dan saat itulah, saat para gerilyawan dimabuk keriangan bermain bola seperti anak-anak, tentara Peru menyerbu masuk dan membunuh mereka semua.
Simak bagaimana Che Guevara menggunakan sepakbola sebagai salah satu alat mengkampanyekan revolusi Sepakbola dalam Hidup Che Guevara
Tentu tak lengkap tanpa mengisahkan Maradona. Cuma orang Argentina ini yang dalam waktu kurang dari 10 menit, dalam pertandingan yang sama, sanggup mencetak dua gol dengan cara yang luar biasa kontrasnya: gol pertama dicetak dengan luar biasa culas lewat tangannya, gol kedua dicetak dengan cara yang luar biasa indah dengan melewati hampir setengah jumlah pemain lawan. Ketika Maradona mengatakan bahwa bukan tangan dia yang mencetak gol, melainkan itu tangan Tuhan, maka lagi-lagi orang dari Amerika Latin yang dalam sekali pukul (melalui tindakan dan kata-kata sekaligus) mencampuradukkan batas antara kenyataan dengan khayalan, antara fakta dan fiksi, antara yang realis dengan yang magis. Mestikah diherankan jika para pemuja Maradona sampai membuat gereja khusus untuknya? Sebagaimana umat Kristiani membagi sejarah ke dalam dua fase yaitu Before Christ/Sebelum (kelahiran) Masehi dan After Christ/Setelah (kelahiran) Masehi, umat gereja Maradona ini juga membagi waktu ke dalam dua periode berdasar tanggal kelahiran Maradona: Before Diego dan After Diego. Gereja Maradona atau Iglessia Maradoniana ini didirikan di Rosario, Argentina. Mereka juga punya 10 Perintah, sebagaimana Perjanjian Lama mengajarkan "The Ten Commandment". Dan sebagaimana umat Kristiani punya "Doa Bapak Kami", mereka juga punya doa yang liriknya berbunyi: Diego kami di lapangan/ dikuduskanlah tangan kirimu/ datanglah keajaibanmu./ jadilah gol-golmu dikenang di dunia ini seperti halnya di surga/ Berikanlah kami pada hari ini, keajaiban kami yang secukupnya/ Ampunilah kesalahan orang-orang Inggris/ sebagaimana kami mengampuni para mafia Napoli/ dan janganlah membawa dirimu ke dalam perangkap offside/ tetapi bebaskan dari kami dari Havelange dan Pele// Itu fakta atau fiksi? Bagi orang seperti Marquez, juga bagi para fanatikus sepakbola Amerika Latin, pertanyaan "fakta atau fiksi" itu tak pernah menjadi pertanyaan besar karena segala hal ajaib itu adalah pemandangan sehari-hari, bagian dari semesta kesadaran dan ingatan kolektif. Fakta atau fiksi? Plata o plomo?
[3]
Dalam sepakbola Amerika Latin, keindahan dan kejahatan adalah dua sisi yang yang tak bisa dipisahkan dari permainan sepakbola. Kejujuran para pemain Latin pada naluri alamiahnya yang selalu ingin bermain bola penuh antusiasme, bersanding dengan kedegilan para pengurus federasi atau klub yang terbiasa menilap uang, memanipulasi laporan pajak, memperkaya diri sendiri dan/atau memakai sepakbola untuk mencuci uang haram.
Kejujuran dan kepolosan Andres Escobar bersanding dan disandingkan dengan mafia kakap seperti Pablo Escobar. Jika belakangan kita sering mendengar jargon "orang baik berkumpul dengan orang baik", di Amerika Latin dan Kolombia, setidaknya seperti yang digambarkan film ini, itu tak berlaku. Andres bermain di klub Nacionale yang dikendalikan Pablo.
Ada banyak orang-orang jujur seperti Andres yang rela berbaik-baik secara tulus dengan para mafia seperti Pablo. Misalnya: Antony de Avilla, salah seorang pemain paling pendek yang pernah bermain di Piala Dunia.
[caption id="attachment_180898" align="alignnone" width="403"] Anthony de Avilla, pemain "cebol" di Piala Dunia 1998.[/caption]
Pemain bertinggi badan 160 cm, yang tampil di Piala Dunia 1998, pernah secara terbuka mengatakan dalam suatu wawancara langsung di televisi kalau gol yang dicetaknya dia dedikasikan untuk kebebasan Miguel dan Gilberto Rodriguez, mafia narkoba yang memiliki klub America Cali, yang sedang berada dalam penjara. Sebagaimana Andres dan Rene Higuita yang berterimakasih pada Pablo untuk semua dedikasinya dalam memberinya karir sepakbola, de Avilla juga berterimakasih pada Rodriguez bersaudara yang telah memberinya kesempatan menjadi pemain sepakbola.
Rodriguez adalah rival Pablo. Jika Pablo membeli klub Nacionale, Rodriguez membeli America Cali. Ada juga mafia narkoba lainnya, Gonzalo Gacha, yang menguasai klub sepakbola bernama Millionarios.
Para mafia inilah yang membesarkan sepakbola Kolombia. Di era ketika para mafia ini menggelontorkan uang ke sepakbola, sepakbola Kolombia sedang meniti kecemerlangan terhebat dalam sejarahnya. Klub-klub bisa membayar pemain dengan layak, fasilitas dan stadion dibenahi, iklim kompetisi jadi penuh persaingan yang vital bagi perkembangan kualitas permainan.
Di era inilah, ketika kartel-kartel narkoba masuk ke sepakbola, untuk pertama kalinya ada klub Kolombia yang menjuarai Copa Libertadores, Piala Champions-nya Amerika Latin, yaitu klub Nacionale-nya Pablo. Siapa kaptennya? Andres Escobar. Kolombia saat itu juga sontak menjad kekuatan penting dalam peta sepakbola Amerika Latin. Siapa yang sanggup mengalahkan Argentina dengan skor 0-5 di Buenos Aires? Ya Kolombia di era ini.
Tapi harga yang diminta memang mengerikan: kekerasan sepakbola meningkat, kematian wasit menjadi hal lumrah, pengaturan skor menjadi hal biasa, pemain menghisap kokain jadi pemandangan lazim, dan sederet hal-hal buruk lain yang sama mengerikannya.
Ini menegaskan kembali tengara yang diberikan Financial Action Task Force, gugus tugas Uni Eropa yang menangani kejahatan finansial, yang pernah mengeluarkan laporan ihwal sepakbola sebagai lahan subur perputaran uang haram.[9]
Anthony de Avilla, pemain "cebol" di Piala Dunia 1998.[/caption]
Pemain bertinggi badan 160 cm, yang tampil di Piala Dunia 1998, pernah secara terbuka mengatakan dalam suatu wawancara langsung di televisi kalau gol yang dicetaknya dia dedikasikan untuk kebebasan Miguel dan Gilberto Rodriguez, mafia narkoba yang memiliki klub America Cali, yang sedang berada dalam penjara. Sebagaimana Andres dan Rene Higuita yang berterimakasih pada Pablo untuk semua dedikasinya dalam memberinya karir sepakbola, de Avilla juga berterimakasih pada Rodriguez bersaudara yang telah memberinya kesempatan menjadi pemain sepakbola.
Rodriguez adalah rival Pablo. Jika Pablo membeli klub Nacionale, Rodriguez membeli America Cali. Ada juga mafia narkoba lainnya, Gonzalo Gacha, yang menguasai klub sepakbola bernama Millionarios.
Para mafia inilah yang membesarkan sepakbola Kolombia. Di era ketika para mafia ini menggelontorkan uang ke sepakbola, sepakbola Kolombia sedang meniti kecemerlangan terhebat dalam sejarahnya. Klub-klub bisa membayar pemain dengan layak, fasilitas dan stadion dibenahi, iklim kompetisi jadi penuh persaingan yang vital bagi perkembangan kualitas permainan.
Di era inilah, ketika kartel-kartel narkoba masuk ke sepakbola, untuk pertama kalinya ada klub Kolombia yang menjuarai Copa Libertadores, Piala Champions-nya Amerika Latin, yaitu klub Nacionale-nya Pablo. Siapa kaptennya? Andres Escobar. Kolombia saat itu juga sontak menjad kekuatan penting dalam peta sepakbola Amerika Latin. Siapa yang sanggup mengalahkan Argentina dengan skor 0-5 di Buenos Aires? Ya Kolombia di era ini.
Tapi harga yang diminta memang mengerikan: kekerasan sepakbola meningkat, kematian wasit menjadi hal lumrah, pengaturan skor menjadi hal biasa, pemain menghisap kokain jadi pemandangan lazim, dan sederet hal-hal buruk lain yang sama mengerikannya.
Ini menegaskan kembali tengara yang diberikan Financial Action Task Force, gugus tugas Uni Eropa yang menangani kejahatan finansial, yang pernah mengeluarkan laporan ihwal sepakbola sebagai lahan subur perputaran uang haram.[9]
Ulasan mengenai laporan Financial Action Task Force tentang kejahatan ekonomi di sepakbola bisa dibaca di sini: Lima Pola Kejahatan Ekonomi dalam Sepakbola
Investasi pada klub-klub sepakbola berskala kecil atau liga yang masih amburadul tata-kelola industrinya, selalu punya kemungkinan merupakan uang haram. Masalah sudah muncul sejak masuknya modal yang asal-usul uangnya tak jelas sehingga mustahil diverivikasi. Liga atau kompetisi yang amburadul, dengan pengelolaan yang tidak transparan, amat disukai oleh para investor haram ini. Banyak klub yang sebenarnya jauh dari potensial dari sisi bisnis, tapi justru amat merangsang para pemilik dan pengelola uang haram untuk menanamkan uangnya. Mereka tak mencari laba, yang mereka cari adalah citra sebagai pribadi populer yang dikenal dan berpengaruh di seantero kota. Dari situlah, mafia dan kartel bisa berinteraksi dengan para penguasa atau pejabat lokal di bangku-bangku VVIP. Dan uniknya, praktik-praktik ilegal itu justru tak harus menunggu sebuah liga benar-benar mapan lebih dulu sebagai sebuah industri. Praktik haram pencucian uang justru sangat marak terjadi di negara-negara dengan industri sepakbola yang sebenarnya masih tanggung atau setengah-setengah. Dari situlah, bandar-bandar dan mafia judi dengan mudah bisa mempermainkan hasil sebuah pertandingan. Mereka, para bandar dan mafia judi itu, dengan senang hati memutarkan dan mencuci uang haram milik siapa pun. Para pemain yang berhutang budi pada para pemimpin kartel dengan mudah diatur untuk melakukan ini itu, blunder ini itu, untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan skenario. Di tempat-tempat yang surealis seperti ini, tak ada tempat bagi para "investor putih" yang benar-benar ingin memutarkan uang bersihnya untuk mencari laba. Resikonya selalu sama: uang para "investor putih" itu akan raib dengan cepat. Oleh siapa? Oleh para pengurus klub atau pejabat federasi. Pada 1989, klub Brasil bernama Vasco da Gama pernah menerima investasi 34 juta dollar dari Nation Bank. Hasilnya? Tak sampai dua tahun, uang itu lenyap. Bukan untuk memperbaiki stadion, membenahi fasilitas latihan atau membangun pusat kebugaran bagi para pemain, tapi dihisap oleh Eurico Miranda, Presiden Vasco da Gama. Pada 1999, seorang pengusaha Amerika Serikat juga pernah menginvestasikan angnya pada klub Corinthians dan Cruzeiro. Bagaimana nasibnya? Sama saja seperti uang milik Nation Bank. Atau perusahaan keju terkenal dari Italia, Parmalat, yang pernah mengakuisisi klub Palmeiras. Uang mereka pun raib tak berbekas dihisap oleh para pejabat federasi dan para pengurus klub. Dan itu bukan semata salah para kartel seperti Pablo. Dalam kasus Brasil, korupsi sepakbola berporos terutama duet mertua-menantu Joao Havelange dan Ricardo Texeira. Jika Havelange menjabat sebagai Presiden FIFA selama 24 tahun (1974-1998), Ricardo Texeira jadi presiden CBF selama 23 tahun (1989-2012). Pada 2012, otoritas Swiss, negara tempat kantor FIFA menumpang, mendakwa mertua-menantu ini menerima suap 41 juta dollar terkait hak pemasaran Piala Dunia 2014. Jika Piala Dunia 2014 ini penuh masalah, ditolak oleh rakyat Brazil yang terus menerus berunjukrasa, ini menjadi hal wajar karena semuanya memang dimulai secara salah. Para cartolas inilah, sebutan Brasil untuk kroniisme, yang membuat pembangunan stadion tersendat-sendat dan penuh masalah. Bayangkan saja, pembangunan Stadion Mane Garrincha yang digunakan untuk Piala Dunia 2014 ini didakwa melakukan penggelembungan dana sampai 200 juta dollar. Selalu ada dua sisi dari permainan berbahaya ini. Dan pilihan ala Pablo, plata o plomo, lagi-lagi menjadi alegori dari paradoks sepakbola Amerika Latin ini.
[4]
Apa yang membuat para kartel, mafia dan koruptor itu bisa bermain dengan aman di sepakbola Amerika Latin? Kuncinya adalah populisme, dan ini pula yang mencirikan kepemimpinan kiri di banyak negara Amerika Latin. Pablo Escobar lagi-lagi menjadi contoh terbaik. Bagi rakyat miskin di Medellin, dia tak ubahnya serupa santo. Siapa yang mau menggelontorkan uang untuk menyulap sebuah penampungan sampah raksasa di Medellin menjadi perumahan layak huni yang diberikan secara cuma-cuma? Pablo ini juga yang membuatkan klinik dan rumah sakit, sekolah dan lapangan bola, juga uang-uang segar yang kadang dibagi secara cuma-cuma. Itu juga yang dia lakukan kepada para jaksa, polisi dan hakim serta pejabat-pejabat pemerintah. Aman sudah. Menampilkan diri sebagai populis yang baik hati, si kaya yang dermawan, selalu melahirkan pesona yang berbeda, apalagi jika itu juga diimbuhi dengan satu hal yang diakui sebagai elemen penting dalam kebudayaan Latin: sepakbola. Sejarah sepakbola, hampir di banyak tempat, tak terkecuali di Amerika Latin, selalu rapat hubungannya dengan rakyat jelata, kaum buruh, atau penduduk miskin yang tinggal di pinggiran kota. Sepakbola selalu menjadi permainan rakyat yang bisa memberi kebahagiaan sederhana, juga harapan akan masa depan yang indah, kepada anak-anak lelaki miskin. Nama-nama seperti Garrincha, Pele, sampai nama-nama yang muncul lebih belakangan seperti Romario, Ronaldo, Ronaldinho, dll., umumnya lahir dari kampung-kampung kumuh di pinggiran kota yang biasa disebut "favela". favela merujuk perkampungan miskin dan kumuh yang berada di punggung-punggung bukit di pinggiran kota. Jika kompleks-kompleks perumahan orang kaya biasanya berada tak jauh dari pantai, orang-orang dari kelas menengah ke bawah Brazil lebih banyak tinggal di favela-favela ini. Seperti yang sempat saya uraikan dalam esai "Piala Dunia dan Kematian Malandro", di favela inilah lahir cerita rakyat mengenai malandro. Sosok malandro adalah anak laki-laki yang dibayangkan sebagai budak yang baru saja dibebaskan dari tuannya (Brazil menghapuskan perbudakan pada 1888 dan enam tahun kemudian, pada April 1894, laga sepakbola dengan aturan main yang baku untuk pertama kali dimainkan di negeri Brazil). Dia punya ciri sebagai bocah yang riang, lincah, penuh trik dan tipu daya. Dia tinggal bersama ibunya dan dia sendiri yang menjaga dan melindungi ibu dan adik-adiknya. Dengan segala kemampuannya, dia mencari makan dan menghidupi keluarganya, entah dengan mencuri di pasar atau mengakali orang-orang kaya laiknya Robin Hood. Jika dikejar oleh polisi atau tukang pukul orang-orang kaya, bocah malandro akan dengan sangat fasih meliuk-liuk di lorong-lorong kotadan dengan penuh trik sanggup meloloskan diri. Rakyat Brazil percaya, jiwa malandro inilah yang menitis pada bocah-bocah dengan bakat sepakbola yang luar biasa. Orang seperti Garrincha, bagi rakyat Brazil, adalah contoh sempurna dari sosok malandro. Dalam alam pikiran seperti ini, kelihaian menggocek bola melewati para pemain lawan sejalan dengan kelihaian menghindari kejaran polisi. Ada paralelisme antara trik melewati tekel para bek di lapangan hijau dengan kecerdikan untuk bertahan hidup dalam kehidupan yang riil dan sulit di favela. Itulah malandro.[10] Para cartolas seperti Pablo yang menguasai klub Nacionale atau Eurico Miranda yang menjadi presiden Vasco da Gama, tahu benar bahwa untuk bisa didukung oleh rakyat mereka hanya perlu memberi orang-orang miskin itu dengan bantuan-bantuan sosial dan tentu saja sepakbola. Sepakbola selalu menjadi alat yang ampuh membangun solidaritas orang-orang miskin terhadap sosok-sosok populis para cartolas yang mengenakan topeng Robin Hood ini. Mereka inilah yang bisa memberi tontonan sepakbola yang bagus secara rutin dan memuaskan hasrat serta emosi bawah sadar orang-orang miskin dengan kejayaan singkat selama 90 menit, tapi mereka juga yang bisa melahirkan tragedi-tragedi tak mengenakkan hati seperti yang dialami Anders Escobar. Ini bukan lagi soal fakta atau fiksi, plata o plomo. Keduanya adalah realisme (sepakbola) Amerika Latin. Inilah barangkali inti dari kesunyian sepakbola Amerika Latin -- sebagaimana Gabriel Garcia Marquez mengatakannya tentang manusia dan sejarah Amerika Latin.
Catatan Kaki
*Naskah ini berasal dari paper yang dipresentasikan dalam diskusi Forum Muda Paramadina pada 20 Juni 2014.
[1] Film The Two Escobars merupakan dokumenter karya Zimbalist bersaudara, Jeff dan Michael. Disusun dengan memanfaatkan ribuan jam dokumentasi tentang sepakbola Kolombia dan sepak terjang Pablo Escobar. Film dokumenter yang rilis pada 2010 ini merupakan bagian dari seri 30 for 30, rangkaian film yang diproduksi oleh ESPN guna merayakan ulang tahun mereka yang ke-30. Simak ulasan Andreas Marbun, salah satu founder Pandit Football Indonesia, terhadap dokumenter The Two Escobars di sini: http://sport.detik.com/aboutthegame/read/2013/06/20/165113/2279308/1493/uang-haram-yang-berujung-tragedi?b991104bcom.
[2] Setiap peraih Nobel akan diminta memberikan pidato di acara penyerahannya, termasuk pemenang Nobel Sastra. Ketika menjadi pemenang Nobel Sastra 1981, Marquez membacakan pidato berjudul The Solitude of Latin America. Anda bisa membacanya di sini: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1982/marquez-lecture.html. Edisi Indonesia-nya bisa dibaca dalam buku Sidang Sastrawan Dunia yang diterbitkan oleh Penerbit Pinus (Yogyakarta, 2004). Kebetulan saya yang menyunting buku tersebut.
[3] Dua tahun lalu saya sudah menulis esai tersendiri mengenai Garrincha. Anda bisa membacanya di sini: http://sport.detik.com/aboutthegame/read/2013/03/06/084733/2186940/1497/garrincha-hedonisme-si-burung-kecil?utm-source=topshare.
[4] José Sérgio Leite Lope merupakan seorang antropolog Brazil yang punya minat mengkaji bentuk-bentuk kebudayaan populer, tidak terkecuali sepakbola. Anda bisa membaca paper The People`s Joy Vanishes di sini: http://www.vibrant.org.br/downloads/v6n2_lopes.pdf.
[5] Novel Love in the Time of Cholera terbit pertama kali pada 1985 dalam bahasa Spanyol (judul aslinya: El amor en los tiempos del cólera), empat tahun setelah Marquez meraih Nobel Sastra. Edisi Indonesia novel ini sudah diterbitkan oleh Penerbit Selasar pada 2010.
[6] Rene Girrard adalah pemikir Prancis, yang menetap di Amerika Serikat. Bukunya yang berpengaruh, Violence and the Sacred dan The Scapegoat, membahas soal arti penting praktik kekerasan dan pengorbanan dalam berbagai ritual keagamaan. Di Indonesia, pemikiran Girrard mengenai hal itu disebarluaskan oleh Sindhunata yang menulis satu buku khusus tentang hal itu. Baca: Kambing Hitam Teori Rene Girrard, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006. Bahan-bahan dari buku Sindhunata itulah yang saya gunakan untuk memahami tragedi Barbosa ini.
[7] Donn Risol. 2010. Soccer Stories: Anecdotes, Oddities, Lore, and Amazing Feats. Nebraska: Board of Regents of the University of Nebraska, hal. 259-260.
[8] Chris Taylor. The Beautiful Game: A Journey Through Latin American Football. London: Victor Gollancz, hal. 14.
[9] Laporan gugus tugas bidang ekonomi Uni Eropa, pada Juli 2009, merilis laporan berjudul Money Laundering Through the Football Sector. Anda bisa membaca lima pola kejahatan pencucian uang dalam sepakbola melalui laporan tersebut. Baca laporan dari dokumennya langsung: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20through%20the%20Football%20Sector.pdf.
[10] Uraian mengenai malandro dan favela ini saya menggunakan bahan yang ditulis Simon Kuper dalam buku Football Against the Enemies (London: Orion Books, 1994), khususnya pada bab 10 yang berjudul "Pele The Malandro".











