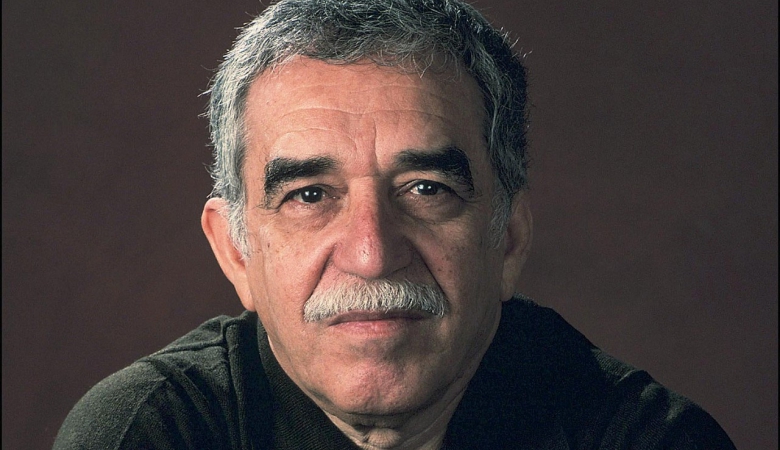Oleh: Arif Abdurahman
Si bocah melihat pertandingan sepakbola pertamanya di London pada 1961, antara Arsenal dan Real Madrid. Sebuah laga persahabatan. Bocah berusia tiga belas setengah tahun itu baru pindah dari Bombay, dan diajak ayahnya ke stadion. Tim London Utara menjamu sang jawara dari Spanyol, yang digadang-gadang sebagai klub terhebat sejagat, yang di dalamnya ada pemain paling hebat sedunia. Keduanya pemain asing: seorang Argentina bernama Alfredo di Stefano dan Ferenc Puskas si jenderal mungil dari Hungaria.
Inilah yang diingat si bocah dari pertandingan itu: di babak pertama, Real Madrid mempecundangi Arsenal habis-habisan. Tiga gol mengoyak gawang tim London yang di masa itu terkenal dengan gaya bermain superdefensif – yang karenanya dilabeli “Boring Arsenal”. Babak pertama: Arsenal 0-3 Real Madrid. Tapi karena ini cuma laga persahabatan, Madrid menarik keluar para pemain bintangnya dan memasukkan para pemain bau kencur. Arsenal tetap dengan pemain utamanya. Hasil akhir: Arsenal 3-3 Real Madrid.
Tentu, bahkan para pendukung Arsenal tahu, kalau hasil akhirnya tak menentukan kualitas asli kedua tim. Pertandingan yang membekas, dan bahkan membelokkan hidup si bocah – jika menganggap pilihan klub sepakbola sama sakralnya seperti pilihan kepercayaan. “Aku enggak terlalu mikirin klub yang Inggris itu,” ungkap si bocah, “tapi aku suka yang Spanyol. Bisakah ayah cari apa ada klub Inggris yang main kayak Real Madrid?” Beberapa hari kemudian, mereka pergi menonton klub lainnya dari London Utara. Sejak saat itulah, si bocah jatuh hati pada Tottenham Hotspur.
Spurs sedang dalam masa tergemilangnya. Dibidani Bill Nicholson, dan dikapteni Danny Blachflower. Musim 1960/61, Spurs memulai dengan 11 kemenangan beturut-turut, permulaan terbaik yang belum pernah diciptakan oleh klub mana pun di Divisi Utama. Selanjutnya, Spurs terus tampil impresif. Dengan tiga pertandingan masih tersisa, gelar diraih saat mereka mengalahkan runner-up Sheffield Wednesday 2-1 di kandang. Double winner berhasil disabet saat Spurs menang 2-0 melawan Leicester di final Piala FA di tahun yang sama.
Ini adalah double winner pertama abad ke-20, dan yang pertama sejak Aston Villa meraih prestasi serupa di tahun 1897. Tahun berikutnya, Spurs kembali memenangi Piala FA setelah mengalahkan Burnley di final. Pada 1963, Spurs juga menjadi tim Inggris pertama yang memenangi trofi tingkat Eropa dengan memenangi Piala Winners 1962/63 berkat kemenangan 5-1 atas Atlético Madrid.
Tahun-tahun berikutnya, Spurs kembali jadi tim medioker. Sementara, rival sekotanya makin membaik, dari Arsenal si membosankan berubah menjadi “Lucky Arsenal”. Si bocah masih terus setia mendukung Spurs. Pada 1999, si bocah yang sudah tidak bocah lagi itu merangkum pengalamannya dalam esai panjang berjudul The People’s Game.
Si bocah itu sudah besar, sudah menjadi penulis, dan kepalanya dihargai 600 ribu dolar atau sekitar 8 triliun rupiah. Bocah itu adalah Salman Rushdie. Berkat novel epic keempatnya, The Satanic Verses (1988), Ayatollah Ruhollah Khomeini, Pemimpin Tertinggi Iran, pada 14 Februari 1989 mengeluarkan fatwa yang menyerukan kematian bagi Rushdie. Penerbitan novel ini menimbulkan kontroversi di dunia Islam karena adanya penggambaran Muhammad yang melecehkan. Judul novel tersebut, ayat-ayat setan, mengacu pada tradisi Muslim yang disengketakan.
Sebagian besar fiksinya berlatar di India, kampung asalnya. Dia menggabungkan realisme magis dengan fiksi sejarah; karyanya berkaitan dengan banyak koneksi, pertentangan, dan migrasi antara peradaban Timur dan Barat. Dan itulah sebenarnya yang juga ingin disampaikan dalam The Satanic Verses.
Sejak tahun 2000, Rushdie telah tinggal di Amerika Serikat. Dia mengakui bahwa sejak dia menghabiskan sebagian besar waktunya di New York, dia lebih banyak menonton pertandingan bisbol ketimbang sepak bola. Menjadi penggemar Yankees. Namun, meski tidak pernah menjadi penggemar agama yang terorganisir, Salman Rushdie tetap memiliki kepercayaan buta untuk tim London utara tadi.
Pada 2006, Rushdie diwawancarai TimeOut London. “Mengapa ada orang yang mengikuti Tottenham Hotspur?” Rushdie tertawa. “Anda harus sangat percaya. Saya datang ke Inggris pada 1961 dan itulah tahun terbaik Spurs. Jika Anda mendukung tim yang gagal memenangi liga selama 44 tahun, itu memang terasa seperti semacam kultus.”
Dari seseorang yang hidupnya telah dirusak begitu dramatis oleh pengikut satu ‘Tuhan’ tertentu, kita bisa memaklumi Rushdie soal pandangannya akan agama. Organisasi agama, tepatnya. Meski demikian, Rushdie dengan senang hati menyesuaikan adagium lama bahwa sepak bola itu sendiri telah menjadi semacam agama. Agama yang lebih penuh keriangan.
Rushdie menggambarkan sebuah perjalanan ke Wembley untuk melihat Spurs bermain melawan Leicester di Final Piala Worthington. Spurs memenangi permainan yang sebenarnya buruk itu dengan gol telak, dan saat Rushdie meninggalkan lapangan, dia terlihat oleh sesama pendukung yang mengenalinya: “Tuhan memberkatimu, Salman,” teriaknya. Rushdie melambai kembali, tapi dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya ingin dia katakan: “Hey, bukan Tuhan; dia tidak bermain untuk tim kita”.
Penulis adalah seorang pegiat Komunitas Aleut. Dapat dihubungi lewat akun Twitter @yeaharip.