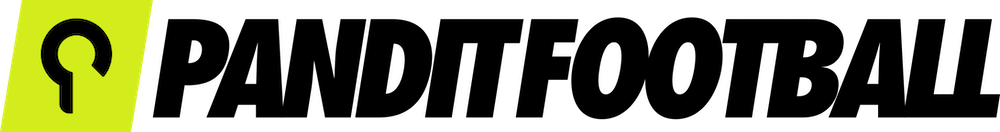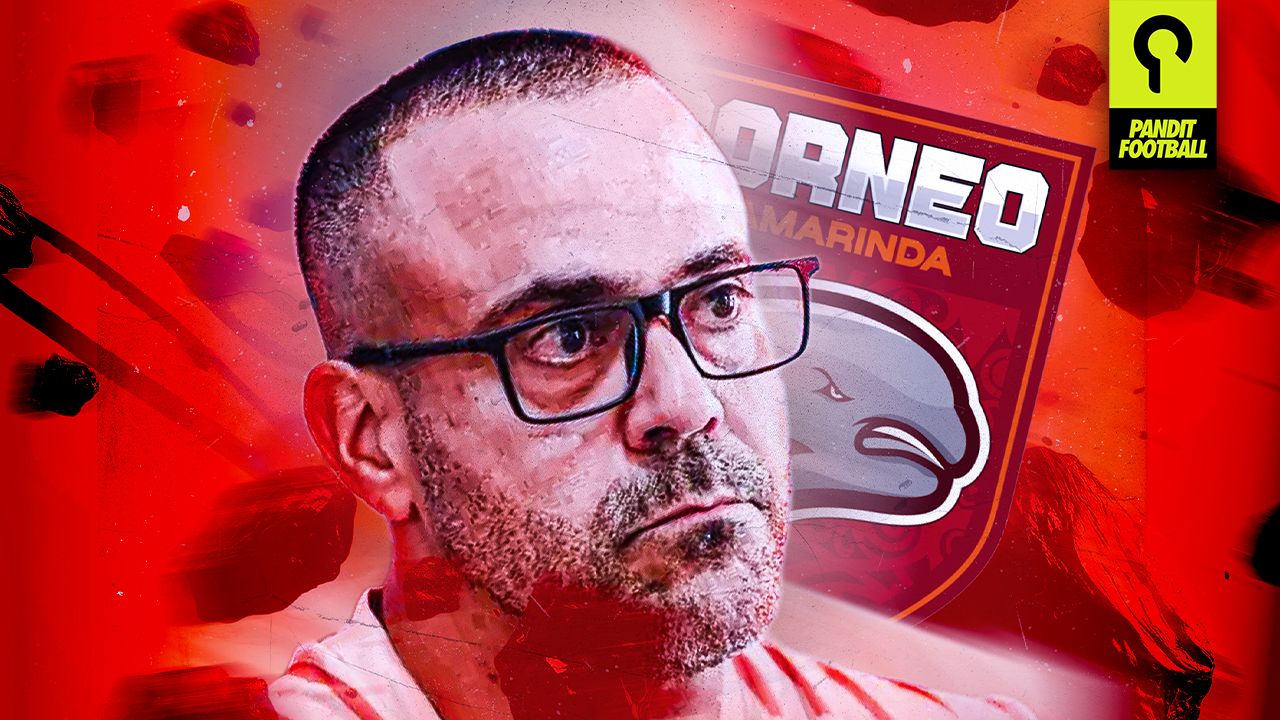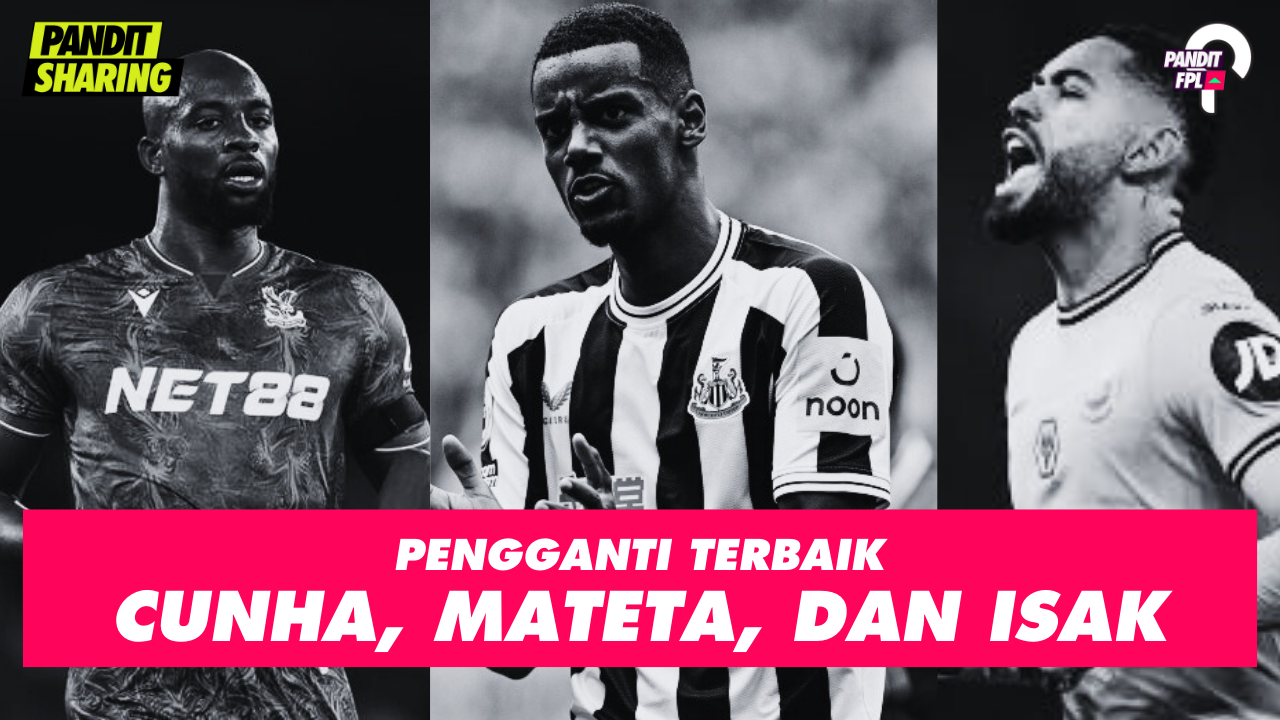Saya masih ingat betul momen di Stadion Siliwangi, ketika kelompok suporter dari Viking Cyber membentangkan spanduk besar bertuliskan “Kick Politics Out of Football.” Saat itu, Persib tengah ramai dimanfaatkan sebagai alat politik elektoral. Spanduk itu bukan sekadar protes, tapi ekspresi keresahan kolektif. Dari situ, muncul pertanyaan: Mungkinkah sepak bola benar-benar bebas dari cengkeraman politik?
Pertanyaan itu terasa penting, meski jawabannya tidak sederhana. Sejak awal berdirinya PSSI pada 1930, sepak bola Indonesia sudah bersinggungan erat dengan politik. Hampir sepanjang sejarahnya, kursi Ketua Umum PSSI selalu diisi oleh tokoh politik atau figur yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari posisi strategis sepak bola sebagai olahraga paling populer di negeri ini.
Sepak bola memiliki daya tarik luar biasa besar. Ia menyentuh berbagai lapisan sosial, membentuk basis massa yang luas dan loyal. Dalam kacamata ilmu sosial, ini disebut sebagai modal sosial—sumber daya yang lahir dari hubungan antarindividu dalam komunitas. Bagi politisi, modal sosial ini sangat berharga. Dukungan suporter bisa diterjemahkan sebagai dukungan elektoral, dan klub sepakbola menjadi kanal komunikasi politik yang efektif.

Jabatan Ketua PSSI bukan hanya soal mengelola organisasi olahraga. Ia juga menjadi figur publik yang berinteraksi dengan pemerintah, media, dan pelaku industri. Popularitas yang melekat pada jabatan ini sering dimanfaatkan sebagai panggung nasional, bahkan batu loncatan menuju jabatan politik yang lebih tinggi.
Dalam praktiknya, kita sering melihat politisi mengenakan atribut klub atau timnas, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka “satu kubu” dengan rakyat. Dalam psikologi politik, kesamaan latar belakang antara politisi dan pemilih dianggap sebagai aset strategis. Pemilih cenderung merasa lebih dekat dan percaya pada figur yang tampak memahami realitas mereka.
Contohnya bisa kita lihat di Italia. Silvio Berlusconi, mantan Perdana Menteri, menggunakan AC Milan sebagai kendaraan politiknya. Ia mengakuisisi klub tersebut dan menjadikannya simbol keberhasilan manajerial dan nasionalisme. Popularitas Milan di bawah kepemimpinannya memperkuat citra Berlusconi sebagai pemimpin yang sukses.
Di Liberia, George Weah—legenda AC Milan dan PSG, serta pemenang Ballon d'Or 1995—memanfaatkan modal sosial dari dunia sepak bola untuk menjadi presiden. Ia membawa narasi “anak rakyat yang sukses di dunia internasional,” sebuah citra yang kuat dan menyentuh.
Lalu, apakah harapan agar sepak bola bebas dari politik adalah hal yang naif? Tidak. Justru itu adalah cerminan dari keinginan suporter akan ruang kolektif yang murni dan jujur. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Sepak bola hampir selalu bersinggungan dengan kekuasaan—baik sebagai alat propaganda, simbol identitas, maupun instrumen ekonomi.
Pada akhirnya, sepak bola adalah permainan rakyat kecil yang telah diambil alih oleh kepentingan politik dan kapitalisme. Politik memanfaatkan sepak bola untuk membangun citra nasionalisme dan stabilitas. Kapitalisme masuk lewat sponsor, hak siar, dan industri merchandise, mengubah klub menjadi korporasi dan suporter menjadi konsumen. Stadion yang seharusnya menjadi ruang rakyat, kini dipagari oleh tiket mahal dan regulasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Suporter pun sering kali menjadi korban. Mereka bukan sekadar penonton, apalagi angka statistik untuk laporan sponsor atau kendaraan politik saat pemilu. Mereka adalah aktor sosial yang memiliki identitas, solidaritas, dan suara kolektif yang kuat. Namun suara itu kerap dibungkam, direduksi, atau dimanipulasi demi kepentingan yang jauh dari semangat sportivitas.
Maka, ketika suporter membentangkan spanduk “Kick Politics Out of Football,” itu bukan sekadar slogan. Itu adalah seruan untuk merebut kembali ruang yang telah lama direbut oleh kekuasaan. Seruan untuk menjadikan sepakbola sebagai milik bersama, bukan alat segelintir elite. Dan meski jalannya panjang, harapan itu tetap hidup di tribun, di mural, di chant, dan di solidaritas yang tak pernah padam.
Saya ingin menutup artikel ini dengan kutipan lirik dari The Business – “Terrace Lost Its Soul”, “Poor man working hard for the rich man, working from the cradle to the grave 30 million for Rio Ferdinand, It looks like it’s the fans who have to pay”.
Tentang Penulis
Nama: Kiki Esa Perdana
Pecinta kehidupan seputar sepak bola yang suka menulis saat subuh sambil menikmati segelas teh hangat dengan sedikit gula.
Email: kikiesaperdana@gmail.com